Buka konten ini

Dosen Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta; Pegiat Kajian Budaya dan Media
DALAM tempo singkat, nasib Sudrajat berbalik 180 derajat bak naskah drama tragikomedi. Pada babak pertama, ia adalah antagonis. Dituduh menjual es jadul berbahaya, dirundung, dan dagangannya dihancurkan oleh klaim sepihak aparat.
Walakin, pada babak kedua, sejurus setelah kasusnya viral, ia berubah menjadi protagonis yang dielu-elukan. Bantuan mengalir deras. Mulai gerobak baru, santunan pendidikan, hingga sepeda motor dari pejabat kepolisian dan bahkan gubernur Jawa Barat.
Penonton merasa lega dengan akhir bahagia di mana si kecil yang teraniaya akhirnya mendapatkan ganti rugi. Namun, di balik euforia kedermawanan itu, terhujam mekanisme kekuasaan yang justru perlu diwaspadai.
Relasi Kuasa
Apa yang dialami Sudrajat tersebut telah menyibak tirai pertunjukan tentang bagaimana kekuasaan bekerja: melukai, lalu membalut luka itu sendiri demi memulihkan citra arogansi kekuasaan.
Seperti diberitakan, persoalan bermula ketika seorang aparat bhabinkamtibmas meremas es dagangan Sudrajat dan dengan penuh percaya diri memvonisnya sebagai busa. Tanpa uji laboratorium, tanpa prosedur saintifik, intuisi aparat dianggap sebagai kebenaran mutlak.
Dalam kacamata Michel Foucault, itu adalah ejawantah relasi power/knowledge. Seragam dinas memberikan legitimasi bagi si pemakai untuk memproduksi ’’kebenaran’’ versi mereka sendiri. Tubuh dan properti rakyat kecil diposisikan sebagai objek disiplin yang seolah boleh diperiksa, dicurigai, dan dihakimi sewaktu-waktu oleh penguasa.
Lebih dari itu, absennya verifikasi sebelum tuduhan dilontarkan menunjukkan arogansi struktural. Bagi aparat, rakyat kecil adalah subjek yang guilty until proven innocent. Es jadul Sudrajat baru dianggap suci kembali setelah viral, alih-alih karena aparat menjunjung asas praduga tak bersalah sejak awal.
Ketika malapraktik kekuasaan itu terungkap, penyelesaian yang hadir tidak kalah problematis. Keadilan bukan menyingsing dari mekanisme koreksi internal kepolisian yang senyap, melainkan melalui lalu lintas viralitas.
Guy Debord dalam The Society of the Spectacle (1967) mengingatkan, realitas modern telah digantikan oleh representasi. Penderitaan Sudrajat dikonsumsi sebagai konten. Maka, solusinya pun harus bersifat visual dan spektakuler. Permintaan maaf saja tidak cukup. Ia harus fotogenik dengan seremonial penyerahan gerobak dan sepeda motor.
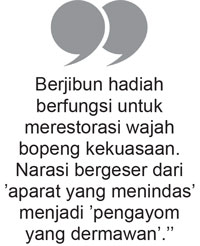 Properti Panggung
Properti Panggung
Dalam kerangka performance studies, bantuan material tersebut, meski nyata manfaatnya bagi korban, sebetulnya berfungsi sebagai properti panggung. Ia menggeser fokus publik dari problem banalitas aparat menjadi pertunjukan kesalehan pejabat.
Di sini, keadilan menjadi komoditas visual. Jika kasus itu tidak direkam dan diunggah ke media sosial, apakah Sudrajat akan disantuni? Sangat mungkin tidak.
Maka ini adalah preseden buruk. Keadilan hanya tersedia bagi mereka yang penderitaannya cukup menjual untuk ditonton.
Dalam buku Strange Encounters, Sara Ahmed membongkar bagaimana logika ’’tuan rumah’’ (negara/kelompok dominan) sering menggunakan keramahtamahan untuk menegaskan kembali kedaulatan mereka atas orang asing alias liyan.
Dalam kerangka itu, pemberian bantuan kepada Sudrajat dapat dibaca sebagai strategi conditional hospitality (keramahtamahan bersyarat). Setelah sebelumnya negara –lewat aparatnya– memosisikan Sudrajat sebagai ancaman yang harus dienyahkan, kini negara berbalik memeluknya sebagai korban yang harus ditolong.
Ironisnya, pola relasi kekuasaannya jauh dari kata imbang. Posisi negara tetap dominan dan rakyat seperti Sudrajat semakin terdominasi. Dengan memberikan santunan, aparat sedang melakukan politik penebusan dosa (redemption).
Berjibun hadiah itu berfungsi untuk merestorasi wajah bopeng kekuasaan. Narasi bergeser dari ’’aparat yang menindas’’ menjadi ’’pengayom yang dermawan’’.
Hospitalitas semu itu amat mengerikan karena ia sama sekali tidak mengubah struktur ketidakadilan yang ada. Sudrajat diterima kembali dalam pelukan masyarakat hanya karena dia bersedia, sadar atau tidak, berperan dalam dramaturgi pemulihan nama baik institusi.
Hal serupa pernah terjadi ketika pendakwah Miftah Maulana viral setelah dianggap merundung penjaja es teh di sebuah pengajian medio 2024. Dalam sekejap, bantuan segera merapat kepada penjual es teh yang bersangkutan, termasuk dari pejabat, politisi, serta pendakwah itu sendiri.
Tentu, bantuan materi adalah hal konkret dan dibutuhkan. Namun, kita tidak boleh terlena oleh romantisasi itu. Yang dibutuhkan publik bukan aparat yang rajin membagikan upeti setelah blunder, melainkan aparat yang sejak awal memiliki standar prosedur ketat dan etika yang luhur dalam memandang dan memperlakukan rakyat kecil.
Keadilan tidak semestinya bergantung pada algoritma media sosial atau belas kasihan pejabat atau aparat. Jika kita berhenti kritis hanya karena melihat foto serah terima bantuan, kita sedang membiarkan kekuasaan terus-menerus mementaskan teater kebaikan untuk menutupi cacat prosedural yang sistemik. Dan, bagi rakyat kecil lain yang nasibnya tidak viral, panggung itu akan tetap gelap gempita, seperti diwedarkan band Sukatani. (*)