Buka konten ini

Dosen Politik Departemen Pemerintahan dan Studi Politik FISIP Universitas Diponegoro Semarang
KETIKA penyedia indeks utama seperti Morgan Stanley Capital International (MSCI) mempertanyakan kelayakan investasi suatu pasar, itu bukan sekadar penilaian, melainkan bekerja sebagai mekanisme pendisiplinan. Bagi banyak investor institusional, indeks bukan opini, melainkan pembatas operasional yang mengikat.
Dalam kasus Indonesia, peringatan MSCI datang dengan tenggat waktu politik yang konkret. Yaitu, jika tidak ada kemajuan yang dianggap memadai dalam transparansi hingga Mei 2026, MSCI dapat mengurangi bobot saham Indonesia dalam indeks Emerging Markets dan bahkan meninjau ulang status aksesibilitas pasar Indonesia.
Situasi itu memunculkan kemungkinan reklasifikasi ke frontier markets, yang pada praktiknya dapat menurunkan visibilitas Indonesia di mata investor institusional besar.
Kerapuhan Likuiditas
Hal tersebut menjelaskan mengapa isu itu berubah menjadi momen mobilisasi total bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengumuman untuk menaikkan persyaratan minimum free float menjadi 15 persen bagi perusahaan tercatat sering dipahami sebagai respons teknis, tetapi sesungguhnya mengandung muatan politik yang dalam.
Langkah itu berupaya mengoreksi fitur struktural kapitalisme ekuitas Indonesia, yakni konsentrasi kepemilikan yang tinggi serta konsekuensi kerapuhan likuiditas yang membuat pembentukan harga lebih rentan terhadap dinamika yang opak dan perilaku yang terkoordinasi.
Di sini, presisi konsep menjadi kunci. Free float tidak sekadar berarti ’’saham di tangan publik’’, tetapi ’’saham yang benar-benar tersedia untuk diperdagangkan’’ sehingga ia merupakan prasyarat bagi kontestabilitas harga. Jika kategori ’’publik’’ mencakup pemegang saham yang secara formal kecil tetapi secara substansi terafiliasi, free float mudah berubah menjadi fiksi regulasi.
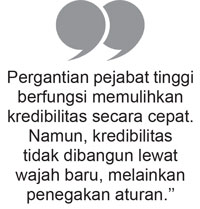 Karena itu, di samping ambang 15 persen, langkah lain yang dibahas sangatlah penting, yaitu pengawasan atas afiliasi di antara pemegang saham di bawah 5 persen. Inilah bagian sensus dari narasi tersebut. Yang dipertaruhkan bukan hanya menaikkan persentase, melainkan merekonstruksi relasi kendali yang dapat disembunyikan oleh persentase itu. Pada titik tersebut, pengunduran diri dan perombakan jabatan tidak dapat dibaca semata-mata sebagai krisis kepemimpinan. Dalam politik kelembagaan, pada momen-momen tertentu, pergantian pejabat tinggi berfungsi memulihkan kredibilitas secara cepat. Ia memberikan sinyal bahwa negara melihat masalahnya dan berniat menanganinya.
Karena itu, di samping ambang 15 persen, langkah lain yang dibahas sangatlah penting, yaitu pengawasan atas afiliasi di antara pemegang saham di bawah 5 persen. Inilah bagian sensus dari narasi tersebut. Yang dipertaruhkan bukan hanya menaikkan persentase, melainkan merekonstruksi relasi kendali yang dapat disembunyikan oleh persentase itu. Pada titik tersebut, pengunduran diri dan perombakan jabatan tidak dapat dibaca semata-mata sebagai krisis kepemimpinan. Dalam politik kelembagaan, pada momen-momen tertentu, pergantian pejabat tinggi berfungsi memulihkan kredibilitas secara cepat. Ia memberikan sinyal bahwa negara melihat masalahnya dan berniat menanganinya.
Namun, kredibilitas tidak dibangun lewat wajah baru, melainkan melalui penegakan aturan. Pertanyaan substantif yang membedakan reformasi nyata dari reformasi ritual adalah apakah aturan-aturan itu akan benar-benar diterapkan ketika menyentuh kepentingan kepemilikan yang kuat dan apakah produksi data mengenai kepemilikan, afiliasi, serta klasifikasi akan stabil, dapat diverifikasi, dan tidak dinegosiasikan kasus per kasus?
Poin yang sering luput, transparansi di sini bukan nilai moral, melainkan teknologi tata kelola. Jika kritik MSCI berkaitan dengan kualitas informasi seperti umpan data, opasitas kepemilikan, atau risiko perilaku terkoordinasi, responsnya tidak cukup berhenti pada lebih banyak pengungkapan. Ia harus menjadi kerja pemetaan yang sistematis.
Sirkuit Terpadu
Di sinilah Bank Indonesia (BI) masuk bukan sebagai pemain pelengkap, melainkan sebagai bagian dari persoalan kepercayaan itu sendiri. Secara teori, bank sentral tidak meregulasi bursa saham. Namun, dalam realitas pasar, kepercayaan bekerja sebagai sirkuit terpadu. Jika ketidakpastian tentang kualitas tata kelola pasar meningkat, sementara keraguan tentang independensi moneter tumbuh secara bersamaan, risiko akan berlipat ganda dan merambat ke nilai tukar, ekspektasi, serta arus modal.
Dalam konteks itu, penunjukan Thomas Djiwandono, yang merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto, sebagai deputi gubernur Bank Indonesia menjadi isu yang diperdebatkan, karena dapat memengaruhi persepsi publik dan pelaku pasar mengenai independensi institusi tersebut.
Tanpa perlu menganggapnya sebagai sebab tunggal gejolak, fakta bahwa isu itu muncul di tengah periode volatilitas memperlihatkan betapa sensitifnya pasar terhadap sinyal-sinyal kelembagaan yang berkaitan dengan otonomi bank sentral.
Keterkaitan antara OJK dan bank sentral tersebut menarik secara politis karena menunjukkan batas retorika teknis. OJK dan BI kerap dipertahankan sebagai otoritas yang netral. Namun, ketika sistem memasuki tekanan, teknik memperlihatkan sifat politiknya. Ini adalah keputusan tentang aturan, hierarki informasi, dan di atas segalanya tentang siapa yang menanggung biaya penyesuaian.
Kebijakan free float 15 persen, misalnya, secara implisit mendistribusikan beban karena meminta emiten yang sering dikendalikan kelompok dominan untuk meningkatkan porsi saham yang benar-benar beredar dan diperdagangkan. Sekaligus menuntut negara agar membuat wilayah yang selama ini abu-abu menjadi lebih terbaca dan dapat diawasi.
Dalam kerangka ini, koordinasi antarlembaga masuk akal sebagai sinyal bahwa ini bukan krisis sektoral. Komunike dari pertemuan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada awal 2026 menegaskan pentingnya penilaian bersama dan stabilitas sistem dalam konteks ketidakpastian global.
Penekanan itu menyiratkan bahwa pasar, nilai tukar, kepercayaan, dan kebijakan ekonomi tidak bergerak secara terpisah. Untuk merumuskannya secara tajam tetapi tidak sinis, episode OJK tersebut bukan semata kronik tentang bursa yang gelisah, melainkan ujian kapasitas negara. Ini adalah ujian atas kemampuan memproduksi informasi yang kredibel, menegakkan aturan melawan kepentingan yang kuat, serta melindungi otonomi lembaga-lembaga kunci ketika tekanan pasar mengubah setiap pilihan menjadi semacam referendum kepercayaan. (*)