Buka konten ini

Wakil Rektor II Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
TAKLIMAT Presiden Prabowo Subianto kepada para rektor dan guru besar pada Kamis (15/1) di Istana Negara patut dibaca melampaui bingkai seremoni kenegaraan. Pertemuan bertema ’’Manusia, Pendidikan Tinggi, dan Sains untuk Kebangkitan Indonesia’’ itu menandai satu kesadaran penting bahwa negara kembali menempatkan kampus sebagai mitra strategis pembangunan bangsa.
Lantaran bobot strategis itulah, forum tersebut juga mengundang pertanyaan reflektif apakah relasi negara dan kampus telah sepenuhnya bergerak dalam watak dialogis yang lebih dewasa, atau masih tertahan dalam tradisi komunikasi yang cenderung satu arah?
Di titik inilah gagasan taklimat dialogis patut dimajukan sebagai orientasi baru relasi negara dengan kampus. Bukan sebagai klaim atas kondisi yang telah ideal, melainkan ikhtiar normatif untuk menuntun relasi negara-kampus ke tingkat kematangan yang lebih tinggi. Negara memang perlu memberikan arah. Namun, kampus dengan nalar, etika, dan kebebasan akademiknya perlu diberi ruang yang cukup untuk menafsirkan, mengkritisi, dan menyempurnakan arah tersebut.
Makna
Secara historis, istilah taklimat berakar dari bahasa Arab ta‘limat, yang dalam tradisi klasik menandai penyampaian arahan strategis, bukan petunjuk teknis keseharian. Taklimat membingkai orientasi besar, tetapi tidak menutup makna. Sebaliknya, arah negara justru menemukan legitimasinya ketika terbuka untuk ditimbang, diuji, dan diperkaya oleh nalar publik.
Dalam konteks dunia akademik, taklimat seharusnya tidak dimaknai sebagai ruang monolog kekuasaan, tetapi undangan berpikir bersama. Presiden telah menempatkan kalangan akademisi sebagai kekuatan intelektual bangsa. Pengakuan penting tersebut akan menemukan maknanya yang utuh ketika kampus benar-benar dilibatkan sebagai subjek pengetahuan, bukan hanya sebagai penerima pesan. Negara yang matang adalah negara yang percaya bahwa kebenaran kebijakan justru menguat ketika diuji oleh argumen ilmiah.
Pada titik ini, taklimat dialogis sejalan dengan gagasan ruang publik deliberatif sebagaimana dikemukakan Jürgen Habermas dalam The Theory of Communicative Action (1981). Kebijakan publik memperoleh legitimasi bukan semata karena kewenangan formal, melainkan karena lahir dari proses komunikasi rasional, tempat argumen diuji secara terbuka dan setara. Dalam kerangka ini, taklimat dialogis bukan hanya soal gaya komunikasi, melainkan fondasi etis bagi kebijakan yang ingin dipercaya dan berumur panjang.
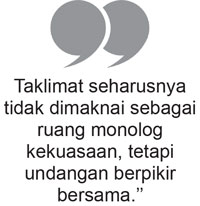 Penekanan presiden pada peran perguruan tinggi sebagai lokomotif penguasaan sains dan teknologi, khususnya dalam agenda pangan, energi, kesehatan, dan industri strategis, menegaskan bahwa pendidikan tinggi diposisikan sebagai fondasi kemandirian bangsa. Komitmen pemerintah untuk meningkatkan dana riset nasional hingga sekitar Rp12 triliun memperkuat pesan bahwa riset tidak dipandang sebagai beban anggaran, tetapi investasi peradaban.
Penekanan presiden pada peran perguruan tinggi sebagai lokomotif penguasaan sains dan teknologi, khususnya dalam agenda pangan, energi, kesehatan, dan industri strategis, menegaskan bahwa pendidikan tinggi diposisikan sebagai fondasi kemandirian bangsa. Komitmen pemerintah untuk meningkatkan dana riset nasional hingga sekitar Rp12 triliun memperkuat pesan bahwa riset tidak dipandang sebagai beban anggaran, tetapi investasi peradaban.
Namun, investasi hanya bermakna jika ditopang oleh etika. Ilmu pengetahuan hanya tumbuh subur dalam iklim kebebasan, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam konteks inilah pemikiran Nurcholish Madjid (1997) menjadi relevan bahwa ilmu harus bebas agar jujur, dan jujur agar bermakna. Kebebasan akademik bukan kemewahan, melainkan syarat moral agar ilmu tidak kehilangan nurani dan orientasi kemanusiaannya.
Dorongan agar riset dihilirkan dan benar-benar berdampak bagi masyarakat tidak boleh dipahami sebagai upaya menyeragamkan agenda ilmiah atau menjadikan ilmu sekadar alat kebijakan. Sebaliknya, dorongan tersebut harus dibaca sebagai panggilan etis agar pengetahuan tidak terkurung di menara gading.
Dalam kerangka ini, etika akademik menuntut keseimbangan yang jernih. Ilmu tidak cukup berhenti sebagai angka di atas kertas pada jurnal dan indeks, tetapi juga tidak boleh direduksi menjadi alat legitimasi kebijakan. Kampus dipanggil untuk menjaga jarak kritis tanpa kehilangan kepekaan sosial, yang berdiri di antara kebebasan berpikir dan keberpihakan pada kepentingan publik.
Kerangka Etika
Relasi negara dan kampus pada hakikatnya adalah relasi etis, bukan semata-mata relasi administratif. Pancasila tidak berhenti sebagai dasar negara, melainkan bekerja sebagai etika relasi antara negara dan warga, antara kekuasaan dan pengetahuan, antara arah kebijakan dan nalar publik. Dalam kerangka etika inilah, negara memberi orientasi nilai dan tujuan strategis, sementara kampus memastikan bahwa orientasi tersebut dijalankan secara rasional, adil, dan peka terhadap realitas sosial.
Dalam konteks tersebut, taklimat yang masih dominan satu arah layak dibaca sebagai fase transisi, bukan sebagai kegagalan. Pada rangkaian acara tersebut memang tidak tersedia sesi tanya jawab khusus karena keterbatasan waktu dan padatnya agenda kenegaraan.
Namun, penting dicatat bahwa dalam beberapa momen Presiden Prabowo justru berkali-kali mengajak audiens berkomunikasi secara langsung, baik melalui pertanyaan terbuka, interaksi spontan, maupun penegasan bahwa kampus diharapkan aktif merespons arah kebijakan. Sinyal itu menunjukkan bahwa meskipun format acara belum sepenuhnya dialogis, kehendak untuk membangun komunikasi dua arah sesungguhnya telah hadir.
Hal ini menandai upaya negara membuka ruang dialog, meski ruang tersebut belum sepenuhnya lapang. Taklimat dialogis hadir sebagai tawaran pendewasaan relasi negara dan kampus, yakni komunikasi yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi membuka deliberasi. Juga, komunikasi yang tidak hanya menggerakkan agenda, tetapi juga mendengarkan nalar dan pengalaman akademik. (*)