Buka konten ini

Guru Besar Kedokteran Bidang Keilmuan Fisiologi Metabolisme dan Aging; Direktur Riset dan Inovasi Universitas Airlangga
AWAL tahun selalu datang dengan dua wajah. Di satu sisi, resolusi hidup sehat kembali digaungkan. Di sisi lain, berat badan justru sering naik diam-diam. Libur panjang, jam makan yang berantakan, dan aktivitas fisik yang menurun menjadi kombinasi klasik.
Fenomena itu bukan perasaan semata. Secara global, lebih dari 43 persen orang dewasa kini tergolong kelebihan berat badan dan sekitar 16 persennya hidup dengan obesitas.
Di Indonesia, angkanya tak kalah mengkhawatirkan. Survei Kesehatan Indonesia 2023 mencatat sekitar 23,4 persen orang dewasa mengalami obesitas. Artinya, hampir satu dari empat orang dewasa Indonesia kini hidup dengan tubuh yang ’’melemak’’. Anehnya, kondisi itu kerap dianggap wajar, bahkan menjadi simbol hidup nyaman dan bahagia.
Obesitas
Padahal, dari sudut pandang kesehatan, obesitas bukan sekadar urusan penampilan. Ilmu fisiologi memberikan gambaran yang lebih jujur. Lemak tubuh, terutama yang menumpuk di rongga perut, bukan sekadar cadangan energi. Ia adalah jaringan aktif yang dapat memicu peradangan. Dalam jumlah berlebihan, lemak justru berubah menjadi sumber masalah. Para ahli menyebutnya sebagai adiposopati atau lemak yang tidak lagi sehat. Dari sinilah berbagai penyakit tidak menular bermula: diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, hingga gangguan metabolik lain yang kini makin sering kita jumpai.
Tubuh manusia sejatinya dirancang untuk hidup seimbang. Ia bekerja mengikuti prinsip homeostasis, menjaga agar segala sesuatu tetap berada dalam batas aman. Masalah muncul ketika asupan energi terus berlebih, sementara gerak tubuh makin minim. Pada awalnya, tubuh masih mampu beradaptasi dengan menyimpan kelebihan energi sebagai lemak. Namun, adaptasi yang berlangsung terlalu lama berubah menjadi masalah. Sensitivitas insulin menurun, peradangan ringan tetapi kronis muncul, dan proses penuaan biologis berjalan lebih cepat. Lonjakan prevalensi obesitas adalah cermin dari ketidakseimbangan itu.
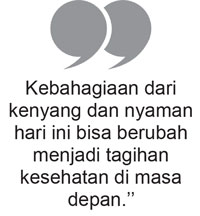 Menurut saya, persoalan obesitas kian rumit karena kita terjebak pada cara pandang yang keliru. Lemak ditakuti, tetapi sekaligus diterima. Kita ingin hidup sehat, namun enggan melepas kenyamanan. Obesitas lalu direduksi menjadi soal disiplin pribadi, seolah cukup diatasi dengan nasihat klise: makan dikurangi, olahraga ditambah. Pendekatan itu tu terlalu sederhana untuk persoalan yang sesungguhnya kompleks.
Menurut saya, persoalan obesitas kian rumit karena kita terjebak pada cara pandang yang keliru. Lemak ditakuti, tetapi sekaligus diterima. Kita ingin hidup sehat, namun enggan melepas kenyamanan. Obesitas lalu direduksi menjadi soal disiplin pribadi, seolah cukup diatasi dengan nasihat klise: makan dikurangi, olahraga ditambah. Pendekatan itu tu terlalu sederhana untuk persoalan yang sesungguhnya kompleks.
Tubuh yang makin ’’melemak’’ sejatinya sedang berbicara. Ia memberikan sinyal bahwa sistem metaboliknya bekerja terlalu keras. Tingginya angka obesitas, baik global maupun nasional, menunjukkan bahwa ini bukan sekadar kesalahan individu. Lingkungan yang membuat tubuh duduk, pola kerja yang panjang, makanan tinggi energi yang mudah diakses, dan minimnya ruang untuk bergerak ikut membentuk masalah. Kebahagiaan dari kenyang dan nyaman hari ini bisa berubah menjadi tagihan kesehatan di masa depan. Di titik ini, lemak bukan lagi tanda kesejahteraan, melainkan alarm yang sering diabaikan.
Pencegahan
Solusinya tidak bisa setengah-setengah. Kita perlu menggeser fokus dari mengobati ke mencegah. Aktivitas fisik, misalnya, tidak boleh dilihat semata sebagai cara membakar kalori. Dari sisi fisiologi, gerak otot adalah sinyal penting bagi tubuh untuk tetap sehat. Aktivitas fisik yang rutin membantu menjaga sensitivitas insulin, menekan peradangan, dan memperlambat penurunan fungsi tubuh akibat usia. Tak perlu ekstrem. Gerak sedang yang konsisten justru lebih realistis dan berdampak luas.
Pengaturan makan pun perlu dipahami secara lebih cerdas. Puasa, termasuk pembatasan waktu makan, bukan sekadar tren gaya hidup. Ia memberi jeda bagi tubuh untuk berhenti menyimpan dan mulai memperbaiki. Namun, puasa tanpa disertai gerak juga menyimpan risiko, terutama hilangnya massa otot. Karena itu, kunci pencegahan obesitas terletak pada keseimbangan: makan teratur dan berkualitas, disertai tubuh yang tetap aktif.
Pada level yang lebih luas, lonjakan obesitas menuntut respons bersama. Lingkungan yang mendukung aktivitas fisik, tempat kerja yang lebih ramah gerak, edukasi kesehatan yang sederhana dan membumi, serta kebijakan yang berpihak pada gaya hidup aktif akan jauh lebih berdampak jika dibandingkan sekadar imbauan. Obesitas adalah persoalan publik, bukan semata urusan klinik.
Pada akhirnya, pertanyaan ’’melemak: bahagia atau berbahaya?’’ patut kita renungkan bersama. Lemak adalah bagian alami dari tubuh. Tetapi, ketika berlebihan, ia berubah menjadi ancaman senyap. Data prevalensi obesitas yang terus naik seharusnya menjadi pengingat. Kebahagiaan bukan soal bebas menikmati tanpa batas, melainkan kemampuan menjaga keseimbangan. Tubuh yang seimbang bukan hanya lebih sehat, tetapi juga memberi kita kesempatan hidup lebih panjang dan bermakna. (*)