Buka konten ini

Dosen Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta; Direktur Eksekutif Politika Research & Consulting
SETIAP kali wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung alias melalui DPRD muncul, reaksi publik hampir selalu sama: menolak. Ingatan kolektif tentang politik dagang sapi di DPRD membuat wacana tersebut terasa seperti langkah mundur. Menolak pilkada lewat DPRD mungkin mudah. Namun, membiarkan pilkada langsung terus berjalan tanpa pembenahan justru lebih berbahaya bagi demokrasi lokal.
Terdapat dua hal ikhwal argumentasi yang sering disampaikan elite politik mengapa pilkada langsung (baca: melalui rakyat) itu perlu dikoreksi. Pertama, alasan yang paling sering dikemukakan adalah tingginya biaya politik. Kontestasi elektoral di tingkat lokal menuntut sumber daya finansial yang besar. Misalnya, biaya kampanye, logistik politik, mobilisasi pemilih, hingga transaksi informal yang kerap sulit dibuktikan seperti politik uang.
Dalam kondisi itu, kepala daerah terpilih masuk ke dalam lingkaran ’’utang politik’’ yang berbahaya. Korupsi kemudian bukan lagi penyimpangan individual, melainkan konsekuensi struktural dari desain politik elektoral itu sendiri.
Alasan kedua, amanat pasal 18 ayat 4 UUD 1945 serta sila keempat Pancasila kerap dijadikan rujukan. Secara normatif, argumen itu tidak sepenuhnya keliru. Namun, persoalannya bukan semata-mata soal ’’boleh’’ atau ’’tidak boleh’’ secara konstitusi, melainkan apa sesungguhnya masalah kebijakan yang ingin diselesaikan?
Masalah Sebenarnya.
Saya jadi teringat buku Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression (Power dan Warburton, 2020). Ada poin menarik dalam buku itu, yakni penjelasan bahwa kemunduran demokrasi di Indonesia terjadi dengan lambat sehingga tidak semua orang bisa merasakannya. Namun, tampaknya, jika pemilihan kepala daerah benar-benar dikembalikan kepada DPRD, mungkin akan lebih jelas kita merasakannya.
Masalahnya bukan pada rakyat sebagai pemilih, tetapi pada desain kompetisi elektoral yang mendorong pembiayaan politik tak terkendali. Mengganti mekanisme pemilihan tanpa membenahi relasi kuasa di tingkat lokal berisiko hanya memindahkan biaya politik, bukan menguranginya. Apakah ada jaminan politik uang akan hilang jika pilkada tidak langsung diberlakukan?
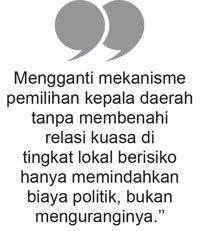 Masalahnya, wacana pilkada melalui DPRD lebih sering hadir sebagai justifikasi, bukan solusi struktural. Ia menawarkan jalan pintas yang tampak sederhana, yaitu memangkas biaya dengan memindahkan arena pemilihan dari rakyat ke parlemen daerah. Padahal, pemindahan mekanisme tidak serta-merta menghilangkan masalah utama seperti tingginya biaya politik dan korupsi. Politik uang tidak lenyap, tetapi berpindah ruang, dari pemilih di TPS ke anggota DPRD, dari kampanye terbuka ke lobi tertutup.
Masalahnya, wacana pilkada melalui DPRD lebih sering hadir sebagai justifikasi, bukan solusi struktural. Ia menawarkan jalan pintas yang tampak sederhana, yaitu memangkas biaya dengan memindahkan arena pemilihan dari rakyat ke parlemen daerah. Padahal, pemindahan mekanisme tidak serta-merta menghilangkan masalah utama seperti tingginya biaya politik dan korupsi. Politik uang tidak lenyap, tetapi berpindah ruang, dari pemilih di TPS ke anggota DPRD, dari kampanye terbuka ke lobi tertutup.
Lebih dari itu, DPRD bukan entitas yang steril dari relasi kuasa. Ia justru kerap kali berada dalam jejaring kepentingan partai politik, elite lokal, atau bahkan oligarki ekonomi daerah. Tanpa pembenahan serius terhadap tata kelola partai politik dan representasi politik di tingkat lokal, pilkada lewat DPRD justru berpotensi mempersempit partisipasi publik dan memperkuat dominasi elite yang itu-itu saja
Di sinilah letak persoalan mendasarnya. Demokrasi lokal kita sedang menghadapi krisis desain, bukan semata-mata krisis prosedur. Pilkada langsung bermasalah. Namun, menghapusnya tanpa membenahi akar persoalan sama saja dengan mengobati gejala, bukan penyakit. Konstitusi dijadikan tameng normatif, sementara permasalahan struktural pembiayaan politik, lemahnya institusionalisasi partai, dan absennya akuntabilitas elite dibiarkan tetap utuh.
Pada 2014, pada masa akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), muncul resistansi publik yang besar ketika disahkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah. Demonstrasi dan penolakan terjadi serta bereskalasi dengan cepat dan luas. Akhirnya, pemerintah pada saat itu memutuskan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Perppu 1/2014) sebagai bukti nyata atas aspirasi rakyat. Lantas, bagaimana opini publik hari ini?
Berdasar hasil survei Politika Research & Consulting (PRC) pada Juni 2025, mayoritas publik menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju (47,9 persen dan 17,8 persen) atas wacana pemilihan kepala daerah dikembalikan secara tidak langsung atau melalui DPRD. Artinya, resistansi publik terhadap wacana itu masih sangat tinggi. Pemerintah perlu mempertimbangkan dengan matang aspirasi publik tersebut sebagai bagian dari proses kebijakan publik.
Solusi
Sepertinya tidak mudah untuk mencari solusi yang kompleks dan struktural dalam pilkada langsung. Jika segala persoalan yang sudah menumpuk itu dilimpahkan kepada rakyat, dengan dihapus hak pilihnya, rasa-rasanya itu sungguh tidak berkeadilan. Terlebih, bukankah pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat adalah syarat minimum bagi merekahnya bunga-bunga demokrasi di Republik Indonesia?
Alternatif kebijakan seharusnya bergerak ke arah yang lebih substansial. Reformasi pembiayaan politik lokal (misalnya soal standar biaya politik) yang harus lebih transparan dengan audit ketat dan penindakan secara tegas terhadap politik uang tanpa pandang bulu perlu dipertimbangkan secara serius. Penguatan rekrutmen dan kaderisasi partai di daerah serta penegakan hukum yang konsisten terhadap korupsi politik merupakan langkah yang jauh lebih sulit, tetapi juga lebih jujur dibandingkan dengan sekadar mengubah prosedur pemilihan.
Demokrasi tidak cukup dipertahankan sebagai prosedur elektoral. Ia juga harus dirawat sebagai sistem yang adil, akuntabel, serta berkelanjutan. Tanpa itu, perubahan mekanisme hanya akan menjadi jalan pintas yang menunda, bukan menyelesaikan, krisis demokrasi di tingkat lokal.
Ini bukan sekedar permasalahan kembali atau tidak kembali ke masa lalu, melainkan soal kegagalan kita menata demokrasi elektoral di tingkat lokal sejauh ini. Pilkada langsung memang menghadapi krisis biaya dan integritas, sementara wacana pilkada lewat DPRD hanya muncul sebagai respons kebijakan yang sesungguhnya problematik. (*)