Buka konten ini

Wakil Dekan 3 FTIK UIN Bukittinggi, Sumatera Barat
10 November merupakan momen yang ditunggu oleh bangsa Indonesia untuk memperingati Hari Pahlawan, yang disambut dengan gegap gempita, mulai dari upacara khidmat hingga serangkaian kegiatan di berbagai daerah. Di televisi, media sosial, hingga ruang kelas, kita mendengar kembali kisah heroik para pejuang yang rela mengorbankan nyawa demi kemerdekaan republik ini. Namun, di tengah arus informasi yang begitu cepat dan hiruk pikuk kehidupan modern, makna kepahlawanan kian terasa kabur. Peringatan Hari Pahlawan sering kali terjebak dalam seremonial belaka, menjadi nostalgia romantik tanpa makna praksis.
Ironisnya, ketika semangat perjuangan seharusnya menjadi energi moral untuk menyelesaikan problematika bangsa, justru yang tampak adalah bangsa yang gamang: dihadapkan pada krisis sosial, maraknya kasus korupsi oleh pejabat, ketimpangan ekonomi, dan degradasi moral.
Maka, pertanyaan penting yang layak diajukan adalah apakah semangat kepahlawanan masih hidup di tengah turbulensi zaman ini? Indonesia hari ini, dalam konteks sosial, sedang menghadapi krisis solidaritas yang cukup mengkhawatirkan. Jika dahulu pahlawan bersatu dalam semangat jargon “merdeka atau mati”, masyarakat hari ini seolah terpecah dalam kotak-kotak identitas sempit—ada sekat politik, agama, ekonomi, hingga preferensi media sosial.
Pola komunikasi publik berubah dari ruang diskusi menjadi arena adu argumen tanpa arah, dari forum musyawarah menjadi timeline perdebatan. Nilai gotong royong yang dahulu menjadi DNA bangsa ini, kini perlahan tergantikan oleh budaya kompetisi yang sering kali mengabaikan empati. Fenomena self-branding di media sosial, misalnya, menciptakan generasi yang lebih sibuk membangun citra diri dibanding membangun relasi yang harmonis.
Pahlawan masa kini dituntut bukan saja mampu mengorbankan diri mereka, melainkan mengorbankan prinsip demi eksistensi digital. Padahal, esensi kepahlawanan sosial adalah keberanian untuk menembus ego dan memperjuangkan harmoni bangsa di atas kepentingan pribadi.
Dari sisi politik, peringatan Hari Pahlawan juga seharusnya menjadi refleksi atas semakin jauhnya jarak antara idealisme perjuangan dan praktik kekuasaan. Dulu, politik adalah alat perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial. Namun kini, politik sering kali menjelma menjadi panggung sandiwara yang lebih mementingkan sisi popularitas dibanding substansi.
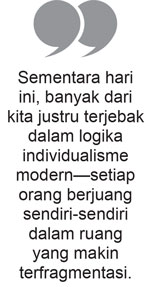 Narasi politik kerap dikemas dengan bahasa kekinian—“politik santuy”, “politik pencitraan”, hingga “politik vibes only”—namun di balik itu, publik makin kehilangan kepercayaan terhadap institusi dan aktor politiknya.
Narasi politik kerap dikemas dengan bahasa kekinian—“politik santuy”, “politik pencitraan”, hingga “politik vibes only”—namun di balik itu, publik makin kehilangan kepercayaan terhadap institusi dan aktor politiknya.
Penyebab pertama, korupsi sudah menjadi penyakit akut yang menggerogoti sistem birokrasi. Kedua, praktik oligarki semakin menguat, menggeser demokrasi yang sesungguhnya menjadi sekadar demokrasi prosedural. Ketiga, polarisasi politik pasca-pemilu sering berlanjut menjadi luka sosial yang tak kunjung sembuh.
Jika dahulu pahlawan berjuang menegakkan kedaulatan bangsa, maka hari ini semangat kepahlawanan seharusnya terwujud dalam perjuangan menegakkan integritas dan etika publik di tengah pragmatisme politik yang semakin banal.
Ironi juga tampak jelas pada bidang ekonomi. Indonesia yang telah dikatakan merdeka selama delapan dekade masih berjuang melawan ketimpangan struktural. Slogan “pahlawan ekonomi” kerap disematkan kepada pelaku UMKM, petani, atau nelayan yang bertahan di tengah keterbatasan. Namun, realitasnya, kebijakan ekonomi dan pertanian kita sering kali masih berpihak pada pemodal besar, bukan rakyat kecil.
Ada ketimpangan ekonomi antara kota dan desa yang terus melebar. Ada ketimpangan generasi muda yang menghadapi fenomena jobless growth, di mana pertumbuhan ekonomi tidak berbanding lurus dengan ketersediaan lapangan kerja.
Ada pula ketimpangan lain dengan munculnya culture of hustle yang menormalisasi kelelahan sebagai simbol kesuksesan. Banyak anak muda yang bekerja bukan karena semangat produktif, tetapi karena takut tertinggal dari teman satu circle.
Semangat heroik untuk memajukan bangsa tergeser oleh semangat bertahan hidup di tengah sistem yang makin keras. Padahal, jika ditarik ke akar makna, ekonomi yang merdeka sejatinya bukan sekadar soal angka pertumbuhan, melainkan tentang kedaulatan ekonomi rakyat—sebuah nilai yang dahulu diperjuangkan dengan darah oleh para pahlawan bangsa.
Sementara itu, dalam ranah pendidikan, problemnya tak kalah kompleks. Sistem pendidikan kita tampak seperti labirin penuh jargon, revisi kurikulum, dan kebijakan silih berganti, namun kehilangan arah nilai. Jika dulu sekolah adalah tempat menanam semangat kebangsaan, kini banyak institusi pendidikan yang terjebak dalam logika kompetisi dan komersialisasi.
Guru dituntut untuk “mengajar dengan gaya abad ke-21”, tetapi sering kali terbelenggu oleh seabrek administrasi dan sistem yang kaku. Sementara siswa dihadapkan pada beban akademik yang besar tanpa cukup ruang untuk belajar menjadi manusia yang seutuhnya.
Fenomena di atas dapat dilihat pada tiga hal. Pertama, pendidikan hari ini cenderung mencetak “manusia paham algoritma”, bukan “manusia penuh karakter”.
Kedua, kesenjangan akses pendidikan antara kota dan desa masih sangat mencolok. Ketiga, digitalisasi pendidikan belum sepenuhnya menyentuh aspek humanistik; pendidikan sering berhenti pada level teknis tanpa diiringi transformasi nilai.
Maka, di tengah situasi seperti ini, pahlawan pendidikan masa kini bukan lagi mereka yang sekadar mengajar, tetapi yang mampu menginspirasi dan menyalakan kembali idealisme belajar sebagai bagian dari perjuangan hidup.
Krisis-krisis di atas sejatinya bersumber dari hal yang sama, yaitu hilangnya roh perjuangan. Pahlawan masa lalu berjuang bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk cita-cita kolektif. Sementara hari ini, banyak dari kita justru terjebak dalam logika individualisme modern—setiap orang berjuang sendiri-sendiri dalam ruang yang makin terfragmentasi.
Inilah yang membuat peringatan Hari Pahlawan sering terasa hambar. Hal ini karena semangat kolektifnya tak lagi hidup di tengah masyarakat yang lebih sibuk mencari cuan, validasi, dan trending topic daripada mencari hakikat makna dari sebuah perjuangan.
Namun, bukan berarti kepahlawanan tidak mungkin hidup kembali. Justru di tengah krisis seperti inilah nilai-nilai kepahlawanan harus dimaknai ulang. Pahlawan abad ke-21 tidak harus mengangkat senjata, tapi harus berani melawan sistem yang tidak adil. Ia bisa berupa jurnalis yang menulis kebenaran di tengah tekanan kekuasaan, aktivis lingkungan yang berjuang melawan perusakan alam, dosen yang tetap idealis di tengah komersialisasi kampus, atau wirausaha muda yang membangun bisnis berbasis etika.
Mereka mungkin tidak viral, tapi karya dan integritasnya menjadi bentuk perlawanan terhadap ketidakberdayaan struktural. Hari Pahlawan seharusnya menjadi momentum nasional untuk menggugat ulang arah perjuangan kita.
Jika dulu semangat kemerdekaan dirumuskan dalam Trisakti Soekarno—berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan—maka hari ini semangat itu bisa diterjemahkan dalam bentuk yang lebih implementatif.
Pertama, berdaulat secara politik berarti menegakkan integritas publik dan membebaskan politik dari oligarki. Kedua, berdikari secara ekonomi berarti membangun sistem ekonomi yang inklusif dan berpihak pada masyarakat kecil. Ketiga, berkepribadian secara sosial-budaya berarti membangun karakter bangsa yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan, bukan sekadar pada global trending.
Ketiga hal di atas, jika dihidupkan kembali, dapat menjadi dasar bagi kelahiran “pahlawan baru”, yaitu mereka yang tidak hanya dikenang karena keberaniannya, tetapi karena relevansinya terhadap tantangan dan perubahan zaman.
Pada akhirnya, menjadi pahlawan di era ini bukan tentang mati di medan perang, melainkan tentang hidup dengan kesadaran penuh di tengah kekacauan zaman. Menjadi pahlawan berarti menolak menjadi apatis, menolak tunduk pada arus pragmatisme, dan menolak untuk berhenti berharap pada bantuan asing.
Di tengah situasi sosial yang makin terpolarisasi, politik yang makin pragmatis, ekonomi yang makin timpang, dan pendidikan yang makin kehilangan arah, kita membutuhkan keberanian untuk mengatakan: “Perjuangan belum selesai!”.
Hari Pahlawan bukan sekadar tentang masa lalu, melainkan tentang siapa yang berani melanjutkan perjuangan hari ini—dengan cara yang baru, di medan yang berbeda, tapi dengan semangat yang sama, yaitu semangat untuk membebaskan manusia dari ketidakadilan dan kebodohan, dalam bentuk apa pun.
Merdeka! (*)