Buka konten ini

Guru Besar Sosiologi Ekonomi FISIP Universitas Airlangga
DI tengah kondisi ekonomi nasional yang sedang tidak baik-baik saja dan suhu politik yang memanas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melontarkan peringatan tegas kepada para kepala daerah serta pejabat publik agar lebih berhati-hati dalam bersikap dan berperilaku. Perlu benar-benar ditimbang agar tidak terjadi ucapan yang salah dan perilaku yang melukai hati masyarakat, terutama di tengah situasi sosial masyarakat yang sedang sensitif.
Tito menegaskan, gaya hidup mewah, pesta berlebihan, hingga pamer kekayaan (flexing) hanya akan menimbulkan persoalan baru dan merusak citra pemerintah. Peringatan keras itu disampaikan Tito saat memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Jakarta awal September lalu.
Dalam forum tersebut, dia menggarisbawahi, para pejabat sebaiknya menunda kegiatan seremonial yang terkesan boros dan tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kesederhanaan dan citra pejabat yang baik mutlak dibutuhkan agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran dari masyarakat.
Kecemburuan Sosial
Kerusuhan massal di Nepal beberapa hari ini merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi para pejabat di tanah air. Di Nepal, sekarang rakyat terbakar amarah. Dimotori generasi Z, rakyat menggelar unjuk rasa besar-besaran menentang sikap elite politik yang hidup mewah di tengah impitan kemiskinan sebagian besar masyarakat.
Di kalangan pengunjuk rasa di Nepal, muncul istilah ’’anak-anak nepo’’ –pelesetan nepotisme– yang viral beberapa minggu menjelang unjuk rasa besar-besaran. Tidak hanya membakar rumah, kantor, dan fasilitas publik, rakyat Nepal yang marah juga menyerang para pejabat. Mereka memukuli dan menelanjangi sejumlah pejabat.
Rakyat marah karena, alih-alih memberikan teladan kesederhanaan, para keluarga pejabat itu justru menampilkan gaya hidup mewah dan suka memamerkan gaya hidup jetset yang memicu kecemburuan sosial.
Beberapa video di platform media sosial seperti TikTok dan Instagram menunjukkan kerabat pejabat pemerintah Nepal dan sejumlah menteri yang bepergian atau berpose di samping mobil-mobil mahal dan mengenakan merek-merek desainer terkenal. Penampilan di luar batas kewajaran itu akhirnya memicu unjuk rasa yang membara.
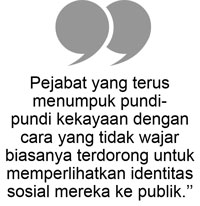 Tidak hanya dituduh korupsi, para keluarga pejabat yang suka flexing dinilai telah mencederai norma kepatutan dan memicu munculnya sikap kritis akibat kesenjangan sosial yang makin terpolarisasi.
Tidak hanya dituduh korupsi, para keluarga pejabat yang suka flexing dinilai telah mencederai norma kepatutan dan memicu munculnya sikap kritis akibat kesenjangan sosial yang makin terpolarisasi.
Di Indonesia sendiri, tren keluarga pejabat yang melakukan flexing mungkin belum seberapa parah sebagaimana di Nepal. Tetapi, indikasi ke arah sana bukan berarti tidak ada. Pengalaman dalam 5–10 tahun terakhir, bisa kita saksikan sejumlah pejabat yang tanpa sadar melakukan flexing dan berperilaku melukai hati rakyat.
Kasus anggota dewan yang berjoget ria di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih banyak didera kemiskinan, terancam PHK, dan lain-lain tentu bisa dipahami jika mengusik hati rakyat. Sensitivitas elite politik yang tidak bersikap empatif pada persoalan yang dihadapi rakyat memicu unjuk rasa di berbagai daerah. Bisa dibayangkan, hati rakyat mana yang tak marah menyaksikan anggota dewan menari-nari riang karena mendapatkan tambahan tunjangan yang luar biasa banyak.
Rakyat tentu masih ingat ketika ada sejumlah pejabat yang menampilkan gaya hidup borjuis di luar batas kewajaran pekerjaan dan gajinya. Bukan sekadar rumah mewah, flexing yang ditampilkan sanak-keluarga pejabat tak sekali dua kali terjadi. Mobil mewah, tas-tas bermerek mahal, bepergian ke luar negeri naik pesawat kelas bisnis, jam tangan mahal hingga puluhan miliar, serta pakaian-pakaian dari brand terkenal adalah hal-hal yang biasa ditampilkan sejumlah pejabat yang merasa eksis.
Keterbukaan
Meminta pejabat tidak melakukan flexing, di satu sisi, memang sudah seharusnya disarankan. Namun, untuk memastikan keluarga pejabat tidak tergoda dan tergelincir memamerkan kekayaannya, yang perlu dilakukan adalah memastikan seberapa jauh kekayaan para pejabat itu benar-benar diperoleh secara halal.
Sumber flexing, diakui atau tidak, adalah pada praktik korupsi yang sudah menjalar ke berbagai sendi kehidupan. Seorang pejabat yang terus menumpuk pundi-pundi kekayaan dengan cara yang tidak wajar biasanya terdorong untuk memperlihatkan identitas sosial mereka ke publik. Menampilkan foto-foto di media sosial seperti aktivitas mereka yang dirasa hebat dan tanpa disadari justru memperlihatkan ketidakwajaran.
Bisa dibayangkan, apa yang berkecamuk di benak warga jika di balik kehidupan gemerlap para pejabat dan elite politik, rakyat ternyata harus menghadapi ancaman PHK di tempat kerja mereka. Usaha yang ditekuni terancam kolaps, harga kebutuhan pokok naik, dan angka pengangguran tak juga turun.
Menurut data BPS, per Februari 2025 masih tercatat 7,28 juta orang yang menganggur. Sementara 59 persen pekerja bertahan di sektor informal, tanpa jaminan sosial, tanpa kepastian masa depan. Dalam situasi seperti itu, tentu bisa dipahami jika rakyat merasa dikhianati dan marah atas pertunjukkan para pejabat.
Untuk memastikan agar rakyat tidak berunjuk rasa, selain mengimbau pejabat tidak flexing, pada saat yang sama, pemerintah perlu menjamin transparansi tentang kekayaan pejabat. Pejabat dilarang merahasiakan kekayaannya. Laporan harta mereka juga perlu diekspos secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban atas jabatan yang diemban. Bagaimana pendapat Anda? (*)