Buka konten ini

Guru Besar dan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya
Kebijakan publik tidak hanya diukur dari hasil akhirnya, tetapi juga dari cara ia lahir. Dalam tradisi demokrasi modern, sebuah kebijakan dianggap sah dan etis bukan semata karena ia memiliki dasar hukum, melainkan karena proses perumusannya melibatkan partisipasi warga dan dilandasi argumentasi yang rasional. Fenomena Bupati Pati Sudewo yang menaikkan pajak hingga 250 persen tanpa konsultasi dan komunikasi publik adalah cermin betapa prinsip itu kerap diabaikan.
Kenaikan pajak daerah memang merupakan salah satu instrumen sah bagi pemerintah untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD). Namun, lonjakan 250 persen bukanlah perkara kecil. Ia berimplikasi langsung terhadap pelaku usaha, petani, nelayan, serta masyarakat umum. Lebih dari sekadar angka, ia menyentuh urat nadi ekonomi warga. Dalam situasi seperti ini, ketiadaan proses komunikasi publik bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga etis.
Etika pejabat publik menuntut adanya tiga prinsip utama: transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Transparansi berarti pemerintah harus membuka data, alasan, dan proyeksi dampak kebijakan. Partisipasi berarti memberikan ruang bagi warga dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan pandangan sebelum kebijakan ditetapkan. Akuntabilitas berarti siap mempertanggungjawabkan kebijakan secara terbuka.
Kenaikan pajak secara sepihak telah mengabaikan ketiganya. Warga tidak mendapatkan informasi memadai, pelaku usaha tidak diberi kesempatan menyampaikan aspirasi, dan mekanisme pertanggungjawaban cenderung bersifat defensif, bukan deliberatif.
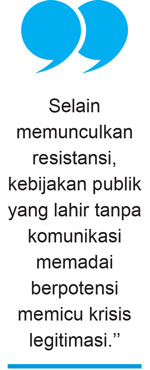 Komunikasi Partisipatif
Komunikasi Partisipatif
Jurgen Habermas, filsuf Jerman yang dikenal dengan Theory of Communicative Action, membedakan dua tipe tindakan sosial. Pertama, tindakan komunikatif yang bertujuan mencapai kesepahaman (mutual understanding) melalui dialog rasional. Kedua, tindakan instrumental yang bertujuan mencapai keberhasilan sepihak (goal-oriented) tanpa mempertimbangkan kesepakatan publik.
Dalam konteks ini, kebijakan bupati Pati cenderung merefleksikan tindakan instrumental. Keputusan diambil untuk mencapai target tertentu –meningkatkan PAD– tanpa proses diskursus publik yang memadai. Legitimasi yang digunakan adalah legitimasi legal-formal (otoritas jabatan), bukan legitimasi diskursif (hasil kesepakatan melalui dialog). Padahal, dalam demokrasi deliberatif, legitimasi diskursiflah yang menjadi roh.
Habermas juga menekankan pentingnya ruang publik (public sphere), yakni arena di mana warga dapat berdiskusi setara tentang isu-isu publik. Ruang itu harus bebas dari dominasi kekuasaan dan terbuka bagi semua pihak. Di sinilah opini publik terbentuk dan dari sinilah legitimasi kebijakan diperoleh. Sebuah kebijakan publik yang lahir dari proses deliberasi cenderung memiliki bobot legitimasi politik yang kuat ketimbang kebijakan yang bersifat sepihak atau top-down.
Ketiadaan forum publik dalam kasus ini menandakan menyempitnya ruang publik. Fenomena menyempitnya ruang publik ditandai oleh tiadanya public hearing, tidak adanya forum konsultasi, dan tidak ada proses uji publik terhadap data maupun argumentasi pemerintah. Kebijakan publik yang lahir di ruang tertutup alias kedap aspirasi hanya akan disambut oleh resistansi warga.
Krisis Legitimasi
Selain memunculkan resistansi, kebijakan publik yang lahir tanpa komunikasi memadai berpotensi memicu krisis legitimasi. Masyarakat mungkin memandang kebijakan tersebut tidak mewakili aspirasi mereka meski secara hukum sah. Kepercayaan yang hilang sulit dipulihkan, dan tanpa kepercayaan, kebijakan sebesar apa pun akan menghadapi resistansi, baik dalam bentuk protes, penghindaran pajak, maupun gugatan hukum.
Dalam konteks proses pembuatan kebijakan publik (public policy making), ’’cara’’ sama pentingnya dengan ’’hasil’’. Bahkan, hasil yang baik tidak akan berarti apabila cara yang digunakan cenderung mengabaikan proses deliberasi publik yang memadai.
Dalam paradigma Habermas, rasionalitas komunikatif berarti membangun kesepahaman melalui pertukaran argumen yang terbuka, setara, dan bebas paksaan. Sebaliknya, rasionalitas instrumental cenderung memandang warga sebagai objek kebijakan, bukan subjek yang setara. Kebijakan pajak di Pati saat ini lebih mencerminkan pola pikir instrumental yang berjalan searah: pemerintah memutuskan, rakyat mengikuti.
Masalahnya, pendekatan instrumental sering kali gagal menangkap realitas di lapangan. Tanpa dialog, pemerintah kehilangan data kontekstual dari warga yang terdampak langsung. Akibatnya, kebijakan berisiko tidak efektif, bahkan kontraproduktif. Kenaikan pajak yang terlalu tinggi, misalnya, bisa memicu penurunan kepatuhan pajak, menghambat investasi lokal, dan mendorong aktivitas ekonomi ke sektor informal yang sulit dipajaki.
Pelajaran Berharga
Dari perspektif teori komunikasi politik Habermas, ada beberapa pelajaran yang dapat diambil. Pertama, ruang publik adalah syarat legitimasi kebijakan. Pemerintah daerah harus memfasilitasi forum dialog sebelum menetapkan kebijakan strategis, apalagi yang berdampak luas. Kedua, partisipasi adalah investasi politik. Melibatkan warga sejak awal mungkin memakan waktu, tetapi hasilnya adalah kebijakan yang lebih diterima dan minim resistensi. Ketiga, transparansi memperkuat kepercayaan. Membuka data dasar penetapan pajak, simulasi dampak, dan pertimbangan alternatif akan menumbuhkan rasa memiliki di kalangan warga.
Kebijakan publik bukan sekadar soal angka atau target PAD. Ia adalah kontrak sosial yang dibangun di atas komunikasi, partisipasi, dan kepercayaan (Rousseau, 1762). Mengabaikan proses deliberasi yang komunikatif berarti mengorbankan fondasi demokrasi itu sendiri. Demokrasi akan rapuh jika proses komunikasinya digantikan oleh logika kekuasaan sepihak. Tanpa dialog, kebijakan kehilangan legitimasi moral. Tanpa legitimasi, ia akan menghadapi perlawanan yang melemahkan efektivitasnya. (*)