Buka konten ini

Dosen Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta; Direktur Serikat Advokat Hak Asasi Manusia
Presiden Prabowo Subianto membuat gebrakan dengan keputusan besar: memberikan amnesti dan abolisi kepada lebih dari seribu orang, termasuk dua tokoh publik, Thomas Trikasih Lembong dan Hasto Kristiyanto. Prosesnya berlangsung cepat—hanya dalam hitungan hari sejak surat presiden dikirim ke DPR hingga keduanya bebas dari tahanan—menjadi simbol kuat “politik pengampunan” di era baru kekuasaan.
Secara konstitusional, langkah itu tidak salah. Pasal 14 UUD 1945 menyatakan bahwa presiden memiliki hak memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Namun, sah secara hukum tidak berarti otomatis tepat secara etik maupun adil secara politik. Amnesti dan abolisi digunakan di luar konteks konflik bersenjata atau pelanggaran berat HAM, serta diberikan kepada figur elite yang sedang tersangkut kasus hukum.
Publik pantas bertanya: untuk siapa sebenarnya pengampunan itu? Apakah ini benar-benar untuk kepentingan bangsa atau bagian dari konsolidasi elite politik yang sedang menyatukan barisan kekuasaan?
Variabel Politik
Sejarah mencatat, amnesti dan abolisi di Indonesia biasanya diberikan dalam konteks konflik politik atau demi rekonsiliasi nasional. Presiden Soekarno menggunakan amnesti untuk merangkul pemberontak PRRI/Permesta. Presiden SBY memberikan amnesti dan abolisi kepada anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) setelah perjanjian damai Helsinki 2005. Gus Dur mengampuni aktivis-aktivis yang melawan Orde Baru karena menganggap mereka sebagai korban ketidakadilan masa lalu.
Namun, dalam kasus Hasto dan Tom Lembong, konteksnya berbeda. Tidak ada konflik politik yang berdarah, tidak ada perjanjian damai, dan tidak ada trauma nasional yang hendak dipulihkan.
Keduanya merupakan tokoh elite: satu teknokrat yang dijerat Kejaksaan Agung karena dugaan korupsi dalam proyek gula, satu lagi politikus partai besar yang ditahan KPK terkait dengan kasus suap. Ketika dua lembaga penegak hukum berbeda menyasar dua figur berbeda, lalu keduanya sama-sama dibebaskan dengan satu keppres, publik mulai melihat pola—dan itu sangat mengkhawatirkan.
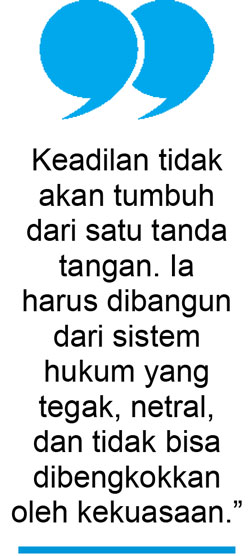 Pertama, hal itu mencerminkan bahwa proses hukum bisa “dibelokkan” atau dibatalkan dengan mudah oleh kekuasaan politik tertinggi. Betul bahwa presiden memiliki hak prerogatif, namun hak itu semestinya digunakan secara selektif, dalam kondisi darurat, dan melalui kajian yang transparan. Jika tidak, keputusan seperti itu justru bisa memperlemah integritas lembaga penegak hukum yang selama ini telah bekerja—terlepas dari segala kekurangannya—membangun kepercayaan publik.
Pertama, hal itu mencerminkan bahwa proses hukum bisa “dibelokkan” atau dibatalkan dengan mudah oleh kekuasaan politik tertinggi. Betul bahwa presiden memiliki hak prerogatif, namun hak itu semestinya digunakan secara selektif, dalam kondisi darurat, dan melalui kajian yang transparan. Jika tidak, keputusan seperti itu justru bisa memperlemah integritas lembaga penegak hukum yang selama ini telah bekerja—terlepas dari segala kekurangannya—membangun kepercayaan publik.
Kedua, ketika DPR sebagai pemberi pertimbangan justru dikuasai partai-partai besar pendukung pemerintah, fungsi kontrol pun tumpul. DPR seharusnya menjadi penyeimbang kekuasaan eksekutif. Namun, dalam kenyataannya, saat ini mereka lebih berperan sebagai “penyambung tangan” pemerintah. Alih-alih mengerem, DPR justru mempercepat gas. Dalam kondisi seperti itu, sistem check and balance tinggal nama. Hukum menjadi variabel politik yang bisa disesuaikan demi kepentingan elite. Mereka yang punya posisi politik strategis akan mendapat ampunan.
Membuka Preseden
Efek jangka panjang amnesti-abolisi itu bukan cuma soal pembebasan dua nama. Lebih dari itu, hal tersebut membuka preseden baru yang bisa dimanfaatkan penguasa di masa depan, bahwa proses hukum bisa ditangguhkan atau dibatalkan untuk alasan yang fleksibel, asalkan ada koalisi politik yang cukup kuat untuk mendukungnya.
Jika kita menerima preseden itu tanpa kritik, pengampunan ke depan bukan lagi soal prinsip, melainkan soal siapa yang dekat dengan kekuasaan. Yang lebih ironis, rakyat kecil yang selama ini dihukum karena unggahan media sosial, unjuk rasa, atau sengketa agraria tidak masuk radar pengampunan. Padahal, merekalah korban nyata dari praktik hukum yang timpang.
Dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan penegakan hukum yang kerap tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Aktivis diseret ke pengadilan, mahasiswa dikriminalisasi karena demo, bahkan jurnalis diintimidasi karena laporan investigatif. Namun sampai hari ini, mereka tak masuk daftar pengampunan.
Jawabannya sederhana: mereka bukan bagian dari elite. Mereka tidak duduk di meja kekuasaan.
Itulah yang membedakan politik pengampunan dengan keadilan substantif. Amnesti dan abolisi bukan sekadar tindakan hukum administratif. Itu merupakan pernyataan politik yang mencerminkan nilai dan arah moral negara. Karena itu, ketika nilai hanya berlaku untuk elite, negara sedang meninggalkan keadilan sebagai fondasi hukum.
Di tengah situasi ini, banyak pihak yang menyambut keputusan Prabowo sebagai “gesture” persatuan. Namun, persatuan tanpa keadilan hanya akan menjadi slogan kosong—apalagi jika tidak disertai reformasi institusional di sektor hukum. Misalnya, memperkuat independensi KPK, membenahi kejaksaan, menertibkan aparat, serta merevisi pasal-pasal karet seperti dalam UU ITE yang selama ini menyasar warga sipil.
Tanpa itu semua, pengampunan seperti ini akan menjadi kosmetik politik belaka. Keadilan tidak akan tumbuh dari satu tanda tangan. Ia harus dibangun dari sistem hukum yang tegak, netral, dan tidak bisa dibengkokkan oleh kekuasaan.
Abolisi dan amnesti memang alat hukum yang sah. Namun, penggunaannya harus berdiri di atas prinsip keadilan dan kepentingan publik yang sebenar-benarnya—bukan demi kompromi elite, bukan demi stabilitas kekuasaan, dan bukan untuk memutihkan kasus hukum yang belum selesai diuji secara terbuka. (*)