Buka konten ini

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2015–2019)
Koperasi kembali dicanangkan sebagai pilar ekonomi kerakyatan oleh Presiden Prabowo Subianto. Strategi itu bukan hal baru. Sejak era kemerdekaan, koperasi diposisikan sebagai kendaraan distribusi keadilan sosial dan alternatif dari sistem ekonomi kolonial yang menindas.
Namun, pertanyaannya, mengapa koperasi di Indonesia lebih sering gagal menjadi kekuatan ekonomi berkelanjutan? Apakah problemnya terletak pada struktur kelembagaan, kepemimpinan, atau justru pada pendekatan negara terhadap koperasi itu sendiri?
Dalam lintasan sejarah, koperasi kerap menjadi bagian dari narasi besar pembangunan nasional, tetapi tidak pernah menjadi aktor utama. Ia tumbuh dalam atmosfer birokrasi dan politik jangka pendek, bukan dalam ruang partisipasi ekonomi warga yang hidup.
Akibatnya, banyak koperasi yang hidup sekadar karena intervensi dana pemerintah, bukan karena kebutuhan ekonomi riil di masyarakat. Begitu dukungan negara berhenti, koperasi pun kehilangan daya hidup. Dalam konteks inilah, agenda koperasi dalam pemerintahan mendatang harus ditinjau secara kritis: jangan sampai hanya menjadi kembang api kebijakan –gemerlap sesaat, lalu lenyap dalam gelap.
Titik Lemah
Ada tiga dimensi penting yang selama ini menjadi titik lemah koperasi di Indonesia. Pertama, politik pembangunan yang bersifat sesaat dan tidak berkesinambungan. Sejak masa Orde Baru, koperasi menjadi bagian dari proyek pembangunan nasional. Pemerintah membentuk koperasi unit desa (KUD) untuk mendistribusikan sarana produksi dan stabilisasi harga pangan.
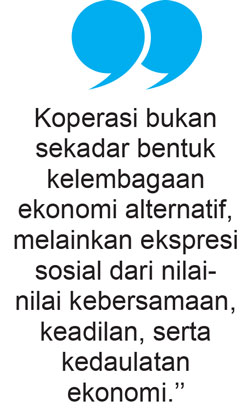 Namun, pendekatan itu bersifat top-down dan menjadikan koperasi sebagai kepanjangan tangan negara, bukan lembaga mandiri yang tumbuh dari kebutuhan dan partisipasi warga. Ketika Orde Baru tumbang, sebagian besar KUD ikut mati.
Namun, pendekatan itu bersifat top-down dan menjadikan koperasi sebagai kepanjangan tangan negara, bukan lembaga mandiri yang tumbuh dari kebutuhan dan partisipasi warga. Ketika Orde Baru tumbang, sebagian besar KUD ikut mati.
Reformasi membuka ruang demokratisasi kelembagaan, termasuk bagi koperasi. Namun lagi-lagi, koperasi gagal menemukan orientasi yang stabil. Banyak koperasi dibentuk sebagai syarat formal untuk menerima bantuan dana desa, program kredit mikro, atau proyek pengentasan kemiskinan. Fokusnya bukan pada penguatan ekonomi anggota, melainkan pada penyerapan anggaran. Karena tidak dibangun dari visi jangka panjang dan tidak dilengkapi desain kelembagaan yang kuat, koperasi hanya menjadi instrumen program, bukan aktor perubahan.
Dalam konteks Prabowo-Gibran, harapan atas koperasi harus dikawal dengan kecermatan struktural. Kebijakan pro-koperasi yang hanya bersandar pada serapan anggaran tidak akan membuahkan dampak ekonomi signifikan. Jika koperasi kembali ditarik masuk ke dalam skema politik elektoral atau proyek lima tahunan, kegagalannya tinggal menunggu waktu.
Kedua, krisis kompetensi dan integritas pengelola koperasi. Banyak pengurus koperasi yang tidak memiliki latar belakang manajerial yang memadai, tidak memahami prinsip tata kelola yang akuntabel, serta lemah dalam membangun transparansi internal. Koperasi yang semestinya menjadi wadah pendidikan ekonomi rakyat justru berubah menjadi lembaga administratif yang statis, tertutup, dan kadang sarat konflik kepentingan.
Lebih dari itu, integritas menjadi persoalan serius. Tidak sedikit koperasi desa maupun kota yang tersandung kasus penggelapan dana, laporan fiktif, atau manipulasi pembagian SHU (sisa hasil usaha). Dalam sistem yang tidak dibangun atas prinsip meritokrasi, jabatan pengurus koperasi sering kali didistribusikan atas dasar kedekatan politis atau kepentingan lokal, bukan kompetensi. Ketika manajemen diserahkan kepada orang-orang yang tidak kapabel dan tidak memiliki komitmen ideologis terhadap prinsip koperasi, yang terjadi bukanlah pemberdayaan, melainkan pembebanan struktural.
Akibatnya, koperasi berubah fungsi: dari motor ekonomi menjadi beban anggaran. Pemerintah menggelontorkan dana pendampingan, pelatihan, hingga bantuan modal. Namun, hasilnya tidak proporsional dengan biaya yang dikeluarkan negara. Tanpa reformasi SDM dan tata kelola, koperasi justru menjadi ironi dari ekonomi rakyat: lahir dari idealisme gotong royong, tetapi mati karena ketidakcakapan dan moral hazard.
Arsitektur Masa Depan
Ketiga, kebutuhan untuk membayangkan ulang koperasi sebagai arsitektur masa depan. Koperasi bukan sekadar bentuk kelembagaan ekonomi alternatif. Ia adalah ekspresi sosial dari nilai-nilai kebersamaan, keadilan, serta kedaulatan ekonomi. Dalam banyak negara seperti Finlandia dan Jerman, koperasi menjadi tulang punggung sektor pertanian, perbankan, hingga energi terbarukan. Kuncinya bukan hanya pada regulasi yang suportif, tetapi kesadaran nasional bahwa koperasi adalah bagian dari strategi pembangunan jangka panjang, bukan instrumen darurat.
Di Indonesia, membayangkan ulang koperasi berarti membebaskannya dari beban romantisme sejarah yang stagnan dan memproyeksikannya ke dalam tantangan abad ke-21: digitalisasi, krisis iklim, dan deglobalisasi. Koperasi harus masuk ke sektor-sektor strategis: koperasi digital, koperasi energi hijau, koperasi pendidikan, hingga koperasi kesehatan. Untuk itu, negara perlu mengembangkan national cooperative innovation strategy yang lintas sektor, lintas generasi, dan lintas kelas sosial.
Koperasi juga harus dikembalikan kepada komunitas. Artinya, negara tidak cukup hanya membuat regulasi atau menyalurkan dana, tetapi perlu memfasilitasi ekosistem dialog, pendidikan, dan advokasi yang menjadikan warga sebagai pelaku utama. (*)