Buka konten ini

Guru Besar Teologi di STT Baptis Indonesia, Semarang
Penilaian kinerja dosen dan peringkat perguruan tinggi di Indonesia kini sangat bergantung pada pemenuhan syarat administratif, terutama jumlah publikasi ilmiah. Pemerintah membutuhkan indikator yang jelas dan terukur untuk menilai kinerja dosen. Salah satunya adalah output riset yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi sebagaimana diatur dalam regulasi terbaru.
Publikasi ilmiah menjadi syarat utama untuk kenaikan jabatan akademik, mulai lektor hingga guru besar, sekaligus menjadi parameter penting dalam menilai kualitas suatu perguruan tinggi. Namun, situasi itu telah menimbulkan dilema besar di kalangan akademisi.
Di satu sisi, persyaratan administratif tersebut memang memicu dosen untuk lebih aktif meneliti dan menulis. Di sisi lain, regulasi seperti itu juga menjebak dosen dalam praktik pragmatis yang mengorbankan kualitas serta integritas penelitian.
Pergeseran Nilai
Karya ilmiah yang dihasilkan sekadar untuk memenuhi kewajiban administratif dan abai terhadap orisinalitas, kualitas, maupun kontribusi nyata terhadap ilmu pengetahuan. Bahkan, publikasi yang dihasilkan kadang hasil plagiarisme, produk ghost writer, atau olahan kecerdasan buatan (AI). Yang terpenting bagi sebagian dosen adalah adanya laporan untuk memenuhi tridarma perguruan tinggi dan syarat kenaikan pangkat, bukan dampak akademik.
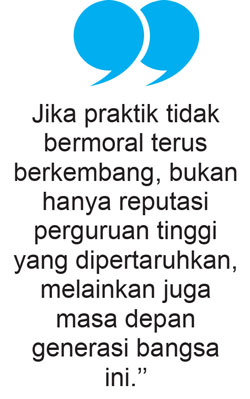 Fenomena lain yang kini marak adalah penggunaan gelar-gelar seperti assistant professor atau associate professor yang lebih menonjolkan aspek prestise daripada jejak ilmiah. Gelar itu digunakan demi gengsi, bukan karena pencapaian akademik yang substansial. Pergeseran nilai tersebut sangat terasa di lingkungan akademik, di mana integritas sering kali dikorbankan demi ambisi jabatan fungsional.
Fenomena lain yang kini marak adalah penggunaan gelar-gelar seperti assistant professor atau associate professor yang lebih menonjolkan aspek prestise daripada jejak ilmiah. Gelar itu digunakan demi gengsi, bukan karena pencapaian akademik yang substansial. Pergeseran nilai tersebut sangat terasa di lingkungan akademik, di mana integritas sering kali dikorbankan demi ambisi jabatan fungsional.
Pencabutan gelar guru besar sejumlah profesor di Universitas Lambung Mangkurat beberapa waktu lalu adalah contohnya. Skandal itu sempat menghebohkan dunia pendidikan tinggi dan membuka mata publik tentang lemahnya sistem pengawasan integritas di lingkungan kampus. Namun, mereka yang tertangkap tangan itu sejatinya hanya sebagian kecil dari masalah yang lebih besar. Sebab, praktik serupa diduga masih banyak terjadi, tetapi belum terungkap dan terkenal sial.
Masalah lain yang tak kalah serius adalah maraknya publikasi di jurnal predator. Banyak dosen Indonesia yang memilih jalur cepat dengan memanfaatkan jurnal-jurnal abal-abal yang menawarkan publikasi instan asalkan berbayar, tanpa proses peer review ketat. Beberapa jurnal predator bahkan sempat terindeks di database ternama seperti Scopus sehingga tetap dianggap sah sebagai syarat kenaikan jabatan.
Fenomena itu menandakan rendahnya kepedulian terhadap kualitas dan integritas penelitian di kalangan akademisi. Selama publikasi tersebut dapat digunakan untuk keperluan administratif, akhirnya kualitas dan etika dikorbankan.
Di tengah berbagai permasalahan itu, Indonesia sebenarnya patut berbangga karena sejumlah perguruan tinggi (PT) tanah air berhasil masuk dalam jajaran QS World University Rankings: South-Eastern Asia 2025. Di antaranya, UI, Unair, UGM, ITB, dan IPB. Prestasi itu menunjukkan bahwa perguruan tinggi Indonesia diakui di tingkat Asia Tenggara, baik dari segi pendidikan, penelitian, maupun profil lulusannya.
Sisi Gelap
Namun, kebanggaan tersebut seolah sirna ketika muncul daftar lain yang mengindeks perguruan tinggi berdasar integritas riset, yakni Research Integrity Risk (RIR). Daftar itu justru mengungkap sisi gelap dunia akademik di mana sejumlah perguruan tinggi ternama masuk kategori Red Flag, High Risk, atau Watch List karena tingginya risiko pelanggaran integritas riset seperti plagiarisme, pemalsuan data, atau publikasi di jurnal predator dipraktikkan pada dosennya. Nama-nama PT itu pun telah beredar luas di masyarakat.
RIR mengukur dua indikator utama, yakni retraction dan D-rate. Retraction terjadi ketika sebuah artikel ditarik kembali dari jurnal karena melanggar integritas, sedangkan D-rate mengacu pada jumlah artikel yang dipublikasikan di jurnal yang kemudian discontinued dari database pengindeks seperti Scopus lantaran dianggap bermasalah.
Fakta bahwa beberapa kampus top Indonesia masuk dalam daftar itu tentu menjadi alarm serius bagi dunia akademik. Penyebab utamanya adalah sistem penilaian yang terlalu menekankan kuantitas publikasi, sementara penilaian terhadap kualitas, impak, dan etika sering kali diabaikan. Banyak dosen yang akhirnya mencari jalan pintas demi memenuhi tuntutan administratif kinerjanya.
Jika situasi itu terus dibiarkan, citra akademik Indonesia akan semakin tercoreng di mata dunia. Diperlukan langkah nyata dan konsisten dari berbagai pihak, mulai pemerintah, perguruan tinggi, hingga komunitas akademik, untuk memperbaiki keadaan.
Pengawasan terhadap publikasi dosen harus diperketat di komite integritas, pelatihan etika riset harus menjadi bagian wajib dalam pengembangan karier dosen, dan budaya akademik yang menekankan kualitas di atas kuantitas perlu ditanamkan sejak dini, bahkan kalau perlu dievaluasi. Sanksi tegas juga harus diberikan, baik kepada individu maupun institusi yang terbukti melanggar, agar tercipta efek jera dan perubahan nyata di lingkungan akademik.
Integritas adalah harga mati dalam dunia pendidikan tinggi. Jika praktik tidak bermoral terus berkembang, bukan hanya reputasi perguruan tinggi yang dipertaruhkan, melainkan juga masa depan generasi bangsa ini. Di era AI, di mana membuat paper ilmiah semakin mudah, membangun budaya akademik yang jujur dan bermartabat menjadi semakin penting –bukan demi gelar atau prestise atau embel-embel profesor di depan nama, melainkan demi masa depan Indonesia yang lebih baik. (*)