Buka konten ini

Guru Besar Manajemen Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya
SETIAP Ramadan tiba, suasana negeri ini berubah hampir serempak. Masjid lebih ramai, pengajian bertambah, dan percakapan tentang kesabaran serta pengendalian diri terdengar di banyak ruang. Di kantor, jam kerja menyesuaikan. Di rumah, waktu berbuka menjadi momen yang ditunggu. Ada nuansa spiritual yang terasa lebih kuat jika dibandingkan dengan bulan lainnya.
Pada saat yang sama, layar ponsel kita dipenuhi promosi. Diskon Ramadan, paket berbuka, promo tiket mudik, hingga parade fesyen Lebaran. Pusat perbelanjaan memperpanjang jam operasional. Platform digital mencatat lonjakan transaksi. Ramadan yang dalam ajaran agama dimaknai sebagai bulan pengendalian diri justru menjadi salah satu puncak konsumsi tahunan.
Menunda Kepuasan
Di sinilah kita berhadapan dengan sebuah ironi. Spiritualitas dan konsumerisme tumbuh bersama. Sebagai akademisi manajemen yang menekuni perilaku dan pengambilan keputusan, saya melihat puasa bukan sekadar ritual keagamaan. Puasa adalah latihan psikologis yang sangat konkret. Selama berjam-jam kita menahan diri dari makan dan minum, dua kebutuhan paling mendasar manusia. Kita menunda kepuasan, mengelola emosi, dan berlatih sabar.
Dalam teori manajemen modern, kemampuan menunda kepuasan merupakan tanda kematangan. Seseorang yang mampu mengendalikan dorongan jangka pendek cenderung lebih rasional dalam mengambil keputusan jangka panjang. Ia tidak mudah tergoda oleh keuntungan sesaat dan lebih mampu memprioritaskan hal yang penting.
Fenomena yang muncul setiap Ramadan sering memperlihatkan gejala sebaliknya. Meja berbuka lebih berlimpah daripada hari biasa. Agenda buka bersama padat hingga melelahkan. Belanja pakaian baru terasa seperti kewajiban sosial. Tradisi memberi pasel atau hampers perlahan berubah menjadi ajang unjuk kemasan dan kemewahan. Tidak ada yang salah dengan merayakan dan berbagi. Perayaan adalah bagian dari syukur. Namun, ketika perayaan berubah menjadi pelampiasan, maknanya bergeser.
Ada kecenderungan psikologis yang patut kita sadari. Setelah seharian menahan diri, sebagian orang merasa berhak memberikan kompensasi berlebih saat berbuka. Setelah sebulan berpuasa, ada dorongan untuk membayar lunas semua penahanan itu pada hari raya. Logika itu manusiawi, tetapi berisiko jika tidak dikendalikan. Ibadah berubah menjadi akumulasi tekanan yang dilepas sekaligus, bukan proses pembentukan karakter.
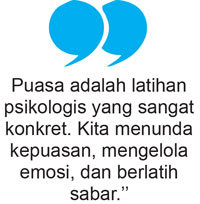 Media sosial memperkuat dinamika ini. Foto takjil yang menarik, restoran berbuka yang estetis, busana Lebaran yang serasi sekeluarga menjadi bagian dari citra diri di ruang digital. Algoritma membaca preferensi kita dengan presisi. Iklan disesuaikan, promosi dipersonalisasi, dan konsumsi dipermudah hanya dengan satu sentuhan. Kita mungkin merasa sedang memilih, padahal sering kali sedang diarahkan.
Media sosial memperkuat dinamika ini. Foto takjil yang menarik, restoran berbuka yang estetis, busana Lebaran yang serasi sekeluarga menjadi bagian dari citra diri di ruang digital. Algoritma membaca preferensi kita dengan presisi. Iklan disesuaikan, promosi dipersonalisasi, dan konsumsi dipermudah hanya dengan satu sentuhan. Kita mungkin merasa sedang memilih, padahal sering kali sedang diarahkan.
Dalam konteks ini, Ramadan menjadi momentum penting bagi industri. Ekonomi memang bergerak melalui konsumsi. Banyak usaha kecil bertahan karena lonjakan penjualan selama Ramadan. Pedagang takjil, penjahit rumahan, hingga pelaku usaha kecil merasakan dampak positifnya. Kita tentu tidak bisa memisahkan Ramadan dari aktivitas ekonomi.
Yang perlu dijaga adalah kesadaran sebagai konsumen. Ada sisi lain yang jarang dibicarakan secara terbuka, yaitu tekanan finansial. Tidak semua keluarga memiliki daya beli yang sama. Di tengah euforia belanja dan tradisi baru, sebagian orang harus bekerja ekstra agar tetap terlihat pantas. Ada yang mengambil cicilan demi membeli gawai baru. Ada yang berutang agar anak-anaknya mengenakan pakaian baru saat Lebaran. Ada pula yang merasa minder karena tidak mampu mengikuti arus. Pada situasi seperti ini, puasa yang seharusnya mengajarkan kesederhanaan justru berisiko memperlebar jarak sosial.
Padahal, salah satu tujuan utama Ramadan adalah membangun empati. Kita diminta merasakan lapar agar lebih peka terhadap mereka yang kekurangan. Kita diajak mengendalikan diri agar lebih bijak dalam menggunakan sumber daya.
Menata Keseimbangan
Sebagai bangsa yang religius sekaligus sedang bertumbuh secara ekonomi, kita berada pada posisi yang tidak sederhana. Di satu sisi, kita ingin ekonomi bergerak dan kesejahteraan meningkat. Di sisi lain, kita tidak ingin kehilangan kedalaman makna spiritual. Tantangannya bukan memilih salah satu, melainkan menata keseimbangan.
Belanja tetap bisa dilakukan dengan perencanaan yang rasional. Buka bersama tetap bisa berlangsung tanpa perlu menjadi kompetisi tempat paling mewah. Memberi tetap dianjurkan tanpa harus disertai kebutuhan untuk dipuji atau dipertontonkan. Kesederhanaan bukan berarti menolak kemajuan, melainkan menempatkan kemajuan dalam batas kewajaran.
Ramadan seharusnya menjadi ruang audit diri tahunan. Kita menilai ulang bukan hanya kualitas ibadah ritual, tetapi juga kualitas keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Apakah kita lebih hemat dalam mengelola pengeluaran. Apakah kita lebih sabar menghadapi perbedaan. Apakah kita lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Jika setelah Ramadan kita kembali pada pola konsumsi yang impulsif dan berlebihan, mungkin ada pelajaran yang terlewat. (*)