Buka konten ini

Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Universitas Riau Kepulauan
SETIAP 25 November, bangsa ini menundukkan kepala mengenang jasa para guru, mereka yang menyalakan peradaban melalui kata dan keteladanan. Namun, di balik peringatan Hari Guru Nasional, masih tersisa pertanyaan yang tak pernah kehilangan relevansi: sudahkah guru Indonesia hidup sejahtera dan bermartabat sebagaimana mestinya? Pertanyaan sederhana yang membawa kita menatap dua sisi realitas: reformasi yang menjanjikan dan realisasi yang belum sepenuhnya berpihak.
Dalam dua dekade terakhir, pemerintah telah berupaya membenahi sistem pembinaan guru melalui berbagai kebijakan. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan langkah besar yang mempertegas status guru sebagai profesi, bukan sekadar pekerjaan. Melalui PPG, lahirlah standar kompetensi, etika, dan legitimasi profesional, sekaligus bentuk nyata perhatian negara terhadap kesejahteraan guru melalui tunjangan profesi. Banyak guru kini hidup lebih layak dan dihargai, menikmati hasil dari perjuangan panjang menuju pengakuan profesional.
Namun di sisi lain, tidak sedikit guru yang tetap tertinggal di pinggir jalan reformasi. Mereka yang telah bertahun tahun mengabdi, terutama di sekolah swasta, kerap terhalang oleh kendala administratif, linearitas ijazah, atau batas usia ketika hendak mengikuti PPG.
Mereka mengajar dengan sepenuh hati, tetapi tanpa jaminan tunjangan profesi. Bagi sebagian dari mereka, usia kini menjadi tembok yang tak bisa ditembus, dan satu-satunya penghasilan hanyalah gaji dari sekolah yang sering kali jauh dari kata layak.
Kondisi ini memperlihatkan adanya jurang yang melebar di antara sesama pendidik. Di sekolah negeri, reformasi berjalan lebih cepat dan fasilitas lebih memadai. Sementara di sekolah swasta, situasinya sangat beragam. Ada yayasan yang kuat secara finansial dan mampu memberikan kesejahteraan memadai bagi gurunya. Namun, banyak pula sekolah yang berdiri dari idealisme, bertahan dengan dana terbatas, dan sangat bergantung pada dedikasi guru-guru yang bekerja bukan demi angka, tetapi karena panggilan hati.
Program pengangkatan guru honorer menjadi ASN-PPPK-PPPK Paruh Waktu juga menghadirkan dua wajah kebijakan. Di satu sisi, ia memberi kepastian status dan kesejahteraan bagi ribuan guru yang telah lama menunggu. Namun di sisi lain, banyak sekolah swasta kehilangan guru-guru terbaiknya setelah mereka diterima sebagai ASN-PPPK-PPPK Paruh Waktu dan harus berpindah ke sekolah negeri. Murid kehilangan sosok pendidik yang sudah menjadi bagian hidup mereka, sementara sekolah kehilangan tenaga berpengalaman yang sulit tergantikan. Ironisnya, guru yang tidak lolos seleksi ASN-PPPK-PPPK Paruh Waktu justru semakin terjepit di tengah kenaikan biaya hidup dan minimnya dukungan finansial bagi Yayasan yang tak cukup kuat menopang.
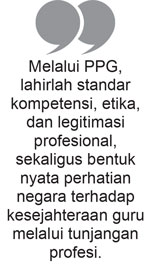 Di luar soal kesejahteraan, guru juga menghadapi tantangan baru di ruang kelas: degradasi moral dan krisis karakter di kalangan siswa. Di era digital yang serba cepat ini, otoritas moral guru kian memudar. Teguran yang dulu mendidik kini bisa dianggap pelanggaran, dan disiplin mudah disalahartikan sebagai kekerasan. Tak sedikit guru yang akhirnya memilih diam karena takut dilaporkan, bahkan dihukum, akibat salah persepsi.
Di luar soal kesejahteraan, guru juga menghadapi tantangan baru di ruang kelas: degradasi moral dan krisis karakter di kalangan siswa. Di era digital yang serba cepat ini, otoritas moral guru kian memudar. Teguran yang dulu mendidik kini bisa dianggap pelanggaran, dan disiplin mudah disalahartikan sebagai kekerasan. Tak sedikit guru yang akhirnya memilih diam karena takut dilaporkan, bahkan dihukum, akibat salah persepsi.
Padahal, tanpa keberanian moral dan kewibawaan, proses pendidikan kehilangan ruhnya. Guru menjadi sosok yang serba salah dan dilematis antara mendidik dengan tegas atau mengajar dengan rasa takut.
Situasi ini menuntut kebijakan yang tidak hanya fokus pada aspek profesionalisme dan tunjangan, tetapi juga perlindungan hukum dan pemulihan wibawa moral guru. Pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, melainkan pembentukan karakter, dan itu hanya bisa lahir dari hubungan yang sehat antara guru dan murid hubungan yang dilandasi kepercayaan, bukan kecurigaan.
Semua dinamika ini menunjukkan bahwa reformasi pendidikan telah bergerak, tetapi belum menyentuh semua lapisan dengan adil. PPG dan Pengangkatan Pegawai adalah kebijakan penting, namun implementasinya belum menata ekosistem guru secara utuh.
Persoalan administrasi, usia, dan status kepegawaian tidak seharusnya menjadi penghalang bagi mereka yang telah lama mengabdi mencerdaskan anak bangsa.
Diperlukan keberanian untuk meninjau ulang sistem agar lebih inklusif dan manusiawi, sehingga setiap guru baik negeri maupun swasta, muda maupun senior memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, sejahtera, dan dihormati.
Guru yang hidup layak akan mengajar dengan cinta, bukan sekadar memenuhi target kurikulum. Guru yang dihargai akan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan kejujuran kepada generasi penerus. Hari Guru seharusnya tidak berhenti pada seremoni dan ucapan terima kasih. Ia adalah pengingat moral bagi kita semua bahwa reformasi pendidikan tidak hanya diukur dari kebijakan yang dirancang, tetapi dari sejauh mana kebijakan itu menghadirkan keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan yang nyata. Karena di ruang kelas yang sederhana, di pelosok yang jauh, masih ada guru yang mengajar dengan cinta, walau kesejahteraannya tertinggal oleh zaman dan di tangan merekalah, masa depan bangsa ini sesungguhnya digenggam. (*)