Buka konten ini

Guru Besar Sains Informasi FISIP dan Kepala Perpustakaan Universitas Airlangga
AKURASI informasi dan pencegahan penyebaran konten-konten disinformasi di media sosial bisa dilakukan melalui sertifikasi influencer (pemengaruh). Wacana perlunya sertifikat kompetensi bagi para influencer itu dinilai penting terutama ketika penyebaran hoaks dan informasi keliru makin marak. Di tengah perkembangan dan akses masyarakat yang makin masif pada berbagai media sosial, kebutuhan akan kode etik, standar, dan mekanisme sertifikasi bagi para influencer menjadi tidak terhindarkan.
Jumlah pemengaruh di tanah air kini terus berkembang. Indonesia dilaporkan menduduki posisi kelima dunia untuk jumlah influencer terbanyak (RRI.co.id). Pada 2024 tercatat ada sekitar 863 ribu influencer aktif (sekitar 3,6 persen) dari total influencer dunia. Jumlah postingan (unggahan) konten influencer Indonesia sepanjang 2024 menempati peringkat keempat dunia, yakni 3,1 juta unggahan.
Pada 2025, jumlah influencer Indonesia diperkirakan lebih banyak. Di Instagram saja, jumlah pemengaruh dilaporkan mencapai 1,1 juta orang. Di YouTube, TikTok, X (Twitter), dan media sosial lain, jumlah influencer dapat dipastikan tidak kalah besar.
Akselerasi perkembangan influencer yang luar biasa pesat itu, jika tidak dikelola dengan baik, dikhawatirkan berisiko berkembang tanpa arah dan melanggar etika. Ketika masih banyak warganet yang belum memiliki fondasi literasi kritis yang kuat, perkembangan influencer dan penyebaran konten-konten di media sosial yang tidak terkontrol dikhawatirkan melahirkan pemahaman yang keliru di masyarakat. Bukan tidak mungkin, masyarakat menjadi salah arah karena dibombardir informasi yang salah dari influencer yang tidak memiliki kompetensi memadai.
Standar Keterampilan
Perlu disadari, influencer di era masyarakat post-industrial bukan sekadar aktivitas di waktu senggang atau hanya penyaluran hobi. Menjadi kreator konten dewasa ini merupakan sebuah profesi yang tidak hanya menawarkan insentif yang sangat memadai, tetapi juga berdampak memengaruhi pola pikir dan perilaku konsumsi serta gaya hidup masyarakat.
Untuk itu, wacana untuk mengatur agar para influencer memiliki standar keterampilan minimal, terutama jika berfokus ke bidang tertentu, sudah selayaknya dilakukan. Ada sejumlah alasan perlunya sertifikasi bagi influencer.
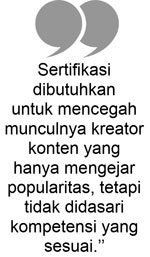 Pertama, untuk memastikan agar kebebasan di era masyarakat digital ini tidak membuat konten kreator memanfaatkannya semata untuk kepentingan komersial dan popularitas tanpa menimbang dampaknya yang merugikan masyarakat.
Pertama, untuk memastikan agar kebebasan di era masyarakat digital ini tidak membuat konten kreator memanfaatkannya semata untuk kepentingan komersial dan popularitas tanpa menimbang dampaknya yang merugikan masyarakat.
Dengan pertumbuhan industri digital Indonesia yang diprediksi mencapai Rp 2.400 triliun pada 2027 (Badan Ekonomi Kreatif, Laporan Ekonomi Kreatif Indonesia, 2024), menjadi kreator konten merupakan peluang yang menjanjikan.
Menjadi pemengaruh yang mampu menawarkan produk tertentu dan membuat konten yang asal beda, bukan tidak mungkin, dapat menjerumuskan masyarakat untuk membeli produk tidak seperti yang dipromosikan. Untuk itu, perlu diatur agar para influencer benar-benar menyampaikan konten yang bisa dipertanggungjawabkan.
Kedua, untuk mencegah masyarakat tidak termakan informasi keliru, baik malinformasi, misinformasi, maupun disinformasi. Menurut data, jumlah warga yang mengakses media sosial belakangan ini meningkat luar biasa. Survei YouGov bersama Vero (2023) melaporkan, 94 persen masyarakat Indonesia terpengaruh konten influencer dan 63 persen mengikuti mereka untuk mencari pengetahuan baru (Vero ASEAN, The Impact of Indonesian Influencers, 2023).
Masalahnya sekarang, ketika influencer menyampaikan informasi yang bukan kompetensi mereka, bukan tidak mungkin informasi yang mereka sampaikan salah. Di media sosial, sekarang ini makin banyak influencer yang berbicara soal pendidikan, ekonomi, kesehatan, hukum, dan isu keuangan tanpa dasar latar belakang akademik yang kuat. Akibatnya, publik mudah menerima informasi tanpa verifikasi. Bahkan, dalam beberapa kasus, masyarakat justru menerima saran yang salah dari konten yang mereka akses.
Ketiga, sertifikasi bagi para influencer dibutuhkan untuk mencegah munculnya kreator konten yang hanya mengejar popularitas, tetapi tidak didasari kompetensi yang sesuai. Apa yang mereka sampaikan bisa saja berisiko pada keselamatan dan kondisi finansial masyarakat apabila salah mengambil keputusan.
Hanya karena mengejar popularitas secara instan, tidak sedikit masyarakat yang tergoda menjadi influencer tanpa mempersiapkan diri secara akademik. Bagi influencer tipe ini, yang penting adalah sensasional dan bagaimana membuat konten-konten bombastis. Tidak sedikit influencer yang tidak memikirkan dampak konten yang mereka buat, asalkan viewer-nya meningkat.
Kredibilitas
Keberadaan influencer sesungguhnya tidak berbeda dengan media massa. Selain ada kode etik, dituntut pertanggungjawaban atas semua konten yang dihasilkan. Influencer tidak diperkenankan memproduksi dan menyirkulasi konten-konten yang bermasalah dan keliru sekadar untuk mengejar popularitas dan jumlah viewer.
Tujuan sertifikasi bagi para influencer sesungguhnya adalah untuk meningkatkan kredibilitas mereka, meningkatkan kualitas konten, dan sekaligus melindungi masyarakat. Persoalannya kemudian, bagaimana wacana sertifikasi influencer ini dijalankan, siapa yang menyertifikasi, dan bagaimana keterlibatan perusahaan platform dalam mengeluarkan sertifikasi.
Di Tiongkok, misalnya, mulai 25 Oktober 2025, Cyberspace Administration of China (CAC) mewajibkan influencer memiliki gelar sarjana atau sertifikat resmi untuk membahas topik profesional seperti hukum, kedokteran, keuangan, dan pendidikan. Di Indonesia, syarat menjadi influencer barangkali tidak harus seperti itu.
Implementasi kebijakan sertifikasi influencer seyogianya tidak menjadi instrumen pembungkam untuk mematikan kreativitas masyarakat, tetapi untuk meningkatkan tanggung jawab dan etika para influencer.
Dengan kebijakan sertifikasi itu, diharapkan dapat terbangun ekosistem digital yang benar-benar sehat dengan konten-konten kreatif yang berkualitas serta bertanggung jawab. (*)