Buka konten ini

Wakil Ketua PWNU Kepri
DI tengah derasnya arus digital dan tayangan yang sering kali menggiring persepsi publik, pesantren kembali diuji bukan oleh kolonialisme bersenjata, melainkan oleh kolonialisme narasi. Kini, bukan peluru yang ditembakkan, tetapi opini dan tayangan yang disebarkan.
Pesantren sejatinya adalah rahim peradaban bangsa. Dari surau kecil di kampung hingga pondok besar di pelosok negeri, di sanalah lahir para pejuang yang menulis sejarah dengan darah dan doa. Saat bangsa ini masih dijajah, para kiai dan santri bukan hanya membaca kitab, tapi juga membaca zaman.
Mereka mendirikan barisan, memanggul bambu runcing, dan berteriak “Allahu Akbar!” di medan tempur. Dari pesantren Tebuireng, Lirboyo, hingga Tremas, lahir tokoh-tokoh yang menjadi pilar kemerdekaan, KH Hasyim Asy’ari, KH Wahid Hasyim, KH Zainul Arifin, hingga para ulama karismatik seperti KH Abbas Buntet, KH Zarkasyi, dan KH Bisri Syansuri.
Mereka tidak hanya berjuang untuk Islam, tetapi juga untuk tanah air. Sebab bagi pesantren, hubbul wathon minal iman — cinta tanah air adalah bagian dari iman. Inilah alasan mengapa pesantren tidak pernah berkhianat pada Indonesia.
Ia berdiri sebagai penjaga moral bangsa, bukan sekadar lembaga pendidikan. Ketika banyak pihak mudah terpecah karena perbedaan, pesantren justru menjadi jembatan persatuan — mengajarkan Islam yang ramah, bukan marah; yang membina, bukan menghina.
Namun kini, marwah pesantren sering kali tercoreng oleh bias tayangan. Di televisi atau media sosial, pesantren kadang digambarkan hanya sebagai tempat yang kolot, kumuh, atau sekadar penghafal kitab tanpa wawasan zaman. Padahal dari balik tembok-tembok sederhana itu, lahir generasi yang berpikir mendalam, berakhlak luhur, dan memiliki semangat juang yang tak pernah padam.
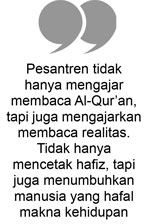 Media seharusnya menjadi cermin yang jernih, bukan kaca benggala yang memantulkan citra miring. Sebab ketika pesantren disalahpahami, sesungguhnya bangsa ini sedang kehilangan salah satu sumber moralitasnya.
Media seharusnya menjadi cermin yang jernih, bukan kaca benggala yang memantulkan citra miring. Sebab ketika pesantren disalahpahami, sesungguhnya bangsa ini sedang kehilangan salah satu sumber moralitasnya.
Pesantren tidak hanya mengajar membaca Al-Qur’an, tapi juga mengajarkan membaca realitas. Tidak hanya mencetak hafiz, tapi juga menumbuhkan manusia yang hafal makna kehidupan.
Kini saatnya publik — terutama media — mengembalikan marwah pesantren. Memberi ruang bagi kisah inspiratif para santri yang berinovasi, para kiai yang berdaya, dan pesantren yang berkontribusi nyata dalam pembangunan bangsa. Sebab di era penuh distraksi ini, pesantren adalah jangkar spiritual yang menahan Indonesia agar tak hanyut oleh arus modernitas yang kehilangan arah.
Pesantren bukan masa lalu, ia adalah masa depan yang sedang ditempa dengan sabar. Di tengah kebisingan dunia digital, pesantren tetap menjaga keseimbangan antara ilmu dan iman, antara akal dan akhlak.
Jika dulu para kiai mengusir penjajah dari bumi Indonesia, maka kini mereka dan para santri sedang berjuang mengusir penjajahan dalam bentuk baru: kebodohan, kemiskinan moral, dan bias informasi. Dan selama semangat hubbul wathon minal iman tetap terpatri di dada para santri, Indonesia akan selalu punya penjaga yang tak lekang oleh waktu. (*)