Buka konten ini

Guru Besar Sosiologi Agama, FISIP, Universitas Udayana
SEBELAN merupakan kata yang sering digunakan masyarakat Bali berkaitan dengan aktivitas keagamaan. Konsep ini mengacu pada pemahaman untuk tidak terlibat dalam berbagai ritual yang diselenggarakan.
Namun, pemahaman umum tersebut berhenti pada titik pelarangan saja, ditambah dengan label “kotor, tidak bersih”, tanpa berupaya mencari akar makna, pengembangan, dan pemanfaatannya. Karena itulah, perempuan yang sedang datang bulan, perempuan hamil, atau mereka yang sedang berduka tidak diperbolehkan masuk ke area persembahyangan. Secara sosial, hal itu terasa tidak adil.
Makna Luas
Pemahaman demikian sangat sempit dan merugikan. Padahal, sebel dan kata sifat sebelan memiliki makna yang baik dan manfaat mendalam apabila dipahami secara lebih luas.
Sebel merupakan kondisi mental yang terganggu oleh suatu keadaan yang menekan. Kondisi demikian berpengaruh pada pola pikir, pola tindak, dan sikap yang cenderung negatif. Kondisi seperti itulah yang dipandang mengganggu sikap persembahyangan. Sebab, pada saat itu diperlukan kondisi mental yang tenang agar doa berlangsung dengan baik.
Ada juga kekhawatiran kondisi mental negatif tersebut mengganggu harmonisasi saat persembahyangan. Misalnya, tiba-tiba mengaduh sakit ketika doa sedang berlangsung.
Jadi, sesungguhnya “pelarangan” itu adalah sebuah izin, nasihat, petunjuk, sekaligus kesempatan untuk beristirahat dan memulihkan kondisi agar kembali baik. Bukan larangan kaku, apalagi dikaitkan dengan sebutan kotor.
Masa Lampau
Banjir di Bali beberapa waktu lalu meluluhlantakkan permukiman di Kota Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Beberapa daerah lain juga terdampak. Banyak rumah di pinggiran sungai tergerus banjir. Di Denpasar, banjir justru terjadi di kawasan yang secara tradisional merupakan pusat aktivitas ekonomi, yaitu pasar dan pertokoan Kumbasari.
Sejak zaman kolonial, bahkan kerajaan, daerah itu telah menjadi pusat perekonomian yang dikenal dengan nama peken payuk (kumba).
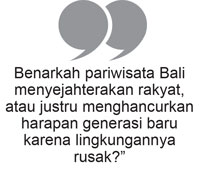 Aktivitas ekonomi masyarakat pada masa lalu berada di pinggiran kali. Dan kali itulah yang beberapa hari lalu meluap, menghanyutkan dagangan serta rumah di sepanjang Tukad Badung. Korban jiwa mencapai belasan orang.
Aktivitas ekonomi masyarakat pada masa lalu berada di pinggiran kali. Dan kali itulah yang beberapa hari lalu meluap, menghanyutkan dagangan serta rumah di sepanjang Tukad Badung. Korban jiwa mencapai belasan orang.
Masyarakat Bali jelas terpukul. Tidak hanya mereka yang terdampak langsung, tetapi juga secara psikologis, karena belum pernah terjadi bencana banjir sebesar itu sebelumnya.
Trauma muncul setiap kali melihat mendung. Kondisi ini tentu tidak sehat. Apalagi, Bali tidak memiliki sejarah yang lurus. Pada ranah politik, penyerangan terhadap Kerajaan Badung dan Klungkung di awal abad ke-20 menewaskan banyak orang. Demikian pula gempa bumi 1917 serta flu Spanyol 1918. Belum lagi tragedi nasional 1965. Semua itu menyisakan horor dalam ingatan.
Karena itu, kondisi pascabanjir 2025 ini merupakan keadaan sebel bagi masyarakat Bali. Mereka sebelan karena kondisi psikologis terganggu. Seperti halnya ketika masyarakat diimbau tidak mengikuti persembahyangan, dalam konteks banjir ini, kegiatan bersifat jangka menengah dan panjang perlu “diistirahatkan” dulu. Inilah saatnya masyarakat melaksanakan “ritual nyepi”.
Kontemplasi
Pada hakikatnya, kebijakan adalah saringan pemikiran yang kemudian diwujudkan dalam bentuk tindakan, keputusan, dan karya. Kebijakan untuk segera membersihkan lingkungan dari kotoran banjir jelas perlu. Keputusan menggerakkan masyarakat bergotong royong juga penting. Cukup itu dulu. Sementara karya jangka panjang ditunda.
Sebaiknya semua berhenti sejenak. Tunda, lalu merenung. Pikirkan apa yang terbaik dilakukan untuk mencegah tragedi di masa depan. Pemerintah, swasta, mahasiswa, perguruan tinggi, semua pihak perlu berkontemplasi.
Pada titik inilah makna Hari Raya Nyepi yang dirayakan setiap tahun oleh masyarakat Hindu Bali menjadi relevan. Dalam keadaan sebelan seperti ini, seluruh komponen masyarakat harus “diam”, nyepi, hening dalam pikiran. Inilah praksis dan manfaat nyepi yang sesungguhnya. Bukan berarti tanpa gerak, tetapi nyepi yang dinamis.
Praksis nyepi adalah berpikir tanpa gejolak, terbuka terhadap kritik, menyerap masukan, membandingkan fenomena bencana, dan berani berkorban. Misalnya, demi keseimbangan alam, tetap bersedia menerima jika kepemilikan hotel berkurang karena terkena penggusuran.
Inti perenungan di Bali adalah keseimbangan pembangunan dengan pariwisata. Itu yang harus direnungkan: benarkah pariwisata di Bali menyejahterakan rakyat, atau justru mengeksploitasi budaya dan merusak lingkungan?
Sudahkah kita paham bahwa Bali hanyalah pulau kecil, sementara sewa buldoser dan traktor merajalela menggerus jurang dan tebing? Sudahkah para pengkavling tanah di pinggir pantai sadar bahwa mereka sesungguhnya membangun “bendungan” yang menghalangi laju air dari hulu?
Pertanyaan-pertanyaan itu akan terus bertambah jika dikaitkan dengan ketidakharmonisan alam Bali saat ini.
Jengah
Satu hal yang tidak boleh ditinggalkan adalah prinsip sosial masyarakat Bali yang diwariskan leluhur: jengah. Di tengah kesibukan mengejar cuan pariwisata, sebagian masyarakat telah melupakan, atau bahkan tidak mengenal, prinsip adiluhung tersebut.
Jengah adalah kata dengan daya luar biasa. Ia bermakna mengakui kegagalan, tetapi bertekad memperbaiki diri; menerima masukan; belajar dari musuh; menghormati guru dan pengalaman; serta bertekad menjaga keseimbangan jiwa untuk memulai sesuatu yang baru demi kemenangan.
Semua itu berakumulasi menjadi satu dalam mempersiapkan diri. Dengan kekuatan itulah sesuatu yang baru dimulai. Jadi, jengah bukan berarti pamer, apalagi balas dendam!. (*)