Buka konten ini

Dosen Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta
Pemerintah baru saja menyetujui pembentukan Kementerian Haji dan Umrah seiring dengan pengesahan Revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Keputusan itu memunculkan pertanyaan penting: Apakah kementerian baru itu sekadar formalitas politik atau benar-benar dapat meningkatkan pelayanan ibadah umat?
Secara simbolis, keberadaan kementerian tersebut menandai prioritas pemerintah terhadap urusan keagamaan. Selama ini, penyelenggaraan haji menjadi bagian dari Kementerian Agama (Kemenag), yang meski memiliki Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta Badan Penyelenggaraan Haji dan Umrah, masih dirasakan kurang optimal dalam koordinasi dan layanan. Dengan kementerian khusus, pemerintah menunjukkan keseriusan dan perhatian khusus terhadap ibadah yang menyentuh jutaan warga Indonesia setiap tahun.
Integrasi Fungsi
Namun, simbolisme semata tidak cukup. Nilai tambah kementerian baru akan terlihat dari kemampuan meningkatkan kualitas pelayanan jemaah haji dan umrah. Kementerian harus mampu menjadi one-stop service, mengintegrasikan fungsi yang sebelumnya tersebar.
Mulai pembinaan, perlindungan, hingga pengawasan dan penataan biaya. Tanpa desain organisasi yang efektif, kementerian baru bisa menjadi beban birokrasi dan anggaran tambahan tanpa dampak nyata bagi jemaah.
Makna sosial kementerian juga layak diperhatikan. Haji bukan sekadar ritual, melainkan simbol identitas umat Islam Indonesia, solidaritas sosial, dan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak beribadah warganya. Kementerian khusus memberikan peluang untuk menerapkan pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis kemanfaatan jemaah. Ini penting karena kualitas pelayanan haji menyangkut kepuasan spiritual dan psikologis jemaah, bukan sekadar administratif.
Selain itu, kementerian baru membuka peluang modernisasi dan inovasi layanan publik. Fokus tunggal pada haji dan umrah memungkinkan pemerintah mendorong digitalisasi pendaftaran, pembayaran dan manajemen jemaah, mempermudah komunikasi, serta memastikan transparansi biaya. Modernisasi itu penting untuk generasi muda yang lebih melek teknologi sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.
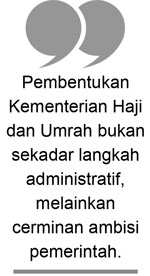 Namun, tantangan nyata tetap ada. Jika kementerian baru hanya menjadi instrumen politik atau formalitas struktural tanpa inovasi nyata dalam pelayanan, dampaknya bakal minimal. Desain kementerian harus menekankan peran fungsional dibandingkan struktural, penguatan kapasitas pegawai, pengawasan internal, serta tata kelola berbasis data. Jika tidak, kementerian justru menambah birokrasi dan pembengkakan anggaran.
Namun, tantangan nyata tetap ada. Jika kementerian baru hanya menjadi instrumen politik atau formalitas struktural tanpa inovasi nyata dalam pelayanan, dampaknya bakal minimal. Desain kementerian harus menekankan peran fungsional dibandingkan struktural, penguatan kapasitas pegawai, pengawasan internal, serta tata kelola berbasis data. Jika tidak, kementerian justru menambah birokrasi dan pembengkakan anggaran.
Pembentukan kementerian juga memiliki implikasi simbolis lebih luas dalam konteks politik identitas dan legitimasi sosial. Ia memberikan sinyal bahwa pemerintah menempatkan urusan spiritual warga negara sebagai prioritas strategis sekaligus mencerminkan sensitivitas terhadap aspirasi masyarakat yang menekankan kualitas ibadah. Jika diiringi kebijakan nyata, simbolisme itu bisa memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah, menunjukkan negara hadir untuk melayani umat, tidak sekadar mengelola administrasi.
Diplomasi Religius
Keberhasilan Kementerian Haji dan Umrah akan diukur bukan dari jumlah pejabat atau struktur, melainkan dari dampak nyata terhadap pengalaman jemaah: keamanan perjalanan, kepastian biaya, kenyamanan fasilitas, dan efisiensi birokrasi. Kementerian ini juga bisa menjadi model reformasi birokrasi berbasis fungsi yang diterapkan pada layanan publik lain di Indonesia.
Selain itu, kementerian baru berpotensi meningkatkan peran Indonesia dalam diplomasi religius internasional. Dengan koordinasi yang lebih terpusat dan profesional, pemerintah bisa lebih efektif bernegosiasi dengan Arab Saudi terkait dengan kuota, fasilitas, dan prosedur haji sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai negara dengan jemaah terbesar yang tertib dan profesional.
Dalam perspektif sosial, pembentukan kementerian dapat memperkuat ikatan emosional antara warga negara dan negara. Ibadah haji adalah pengalaman kolektif yang melibatkan jutaan orang. Pelayanan yang tertata menunjukkan negara peduli pada aspek spiritual dan kesejahteraan warganya. Itu dapat menjadi instrumen untuk membangun solidaritas sosial, memperkuat rasa memiliki terhadap bangsa, dan menunjukkan bahwa negara hadir tidak hanya dalam urusan administratif, tetapi juga dalam pengalaman hidup yang sakral.
Prediksi jangka panjang juga menarik untuk dicermati. Kementerian baru dapat menjadi laboratorium reformasi birokrasi: memadukan struktur fungsional, digitalisasi layanan, dan pendekatan manusiawi bagi jemaah. Jika berhasil, model itu bisa diterapkan untuk layanan publik lain seperti pendidikan, kesehatan, atau administrasi kependudukan.
Namun, kegagalan dalam desain organisasi atau implementasi dapat berakibat pada pemborosan anggaran, birokrasi berlapis, serta ketidakpuasan publik –yang justru akan merusak simbolisme yang ingin dibangun.
Akhirnya, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah bukan sekadar langkah administratif. Ia menjadi cermin ambisi pemerintah: apakah ingin menambah struktur birokrasi semata atau benar-benar menjadi pionir pelayanan ibadah yang modern, aman, dan nyaman. Keberhasilan kementerian itu akan menegaskan bahwa simbolisme birokrasi dapat diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi umat, menjadikan ibadah haji bukan hanya ritual spiritual, melainkan pengalaman layanan publik yang tertata, manusiawi, dan membanggakan.
Pembentukan kementerian tersebut, jika dijalankan dengan desain organisasi yang tepat, juga bisa menjadi warisan kebijakan yang berdampak bagi generasi mendatang. Dengan kata lain, simbolisme kementerian itu hanya akan bermakna jika bisa menyeimbangkan aspek politik, administratif, dan pelayanan publik secara nyata. (*)