Buka konten ini

Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang
Beberapa hari lalu, publik dihebohkan oleh tingkah sebagian anggota dewan yang berjoget-joget kegirangan setelah disahkannya kenaikan tunjangan mereka. Pemandangan itu menjadi ironi besar di tengah jeritan rakyat yang makin sulit memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Harga beras melambung, biaya pendidikan mencekik, sementara angka pengangguran terus membengkak.
Di sisi lain, wakil rakyat yang seharusnya menjadi cerminan empati justru larut dalam euforia yang menusuk rasa keadilan publik. Joget kenaikan tunjangan oleh orang-orang “terhormat” itu mempertontonkan potret mentalitas sebagian anggota dewan yang gagal paham terhadap penderitaan rakyat. Mereka seakan hidup di ruang hampa dan terasing dari realitas sosial yang sesungguhnya.
Rakyat kecil dipaksa mengencangkan ikat pinggang, sedangkan para wakilnya menari di atas penderitaan yang mereka wakili. Tindakan itu tidak saja menyakitkan, tetapi juga memperkuat jurang psikologis yang kian menganga antara elite dan rakyat. Potret buruk semacam itu memperpanjang daftar kelakuan anggota dewan yang sering mencoreng citra lembaga legislatif.
Paradoks
Selama ini, publik sudah sering menyaksikan wakil rakyat tidur saat sidang, terlibat kasus korupsi, hingga studi banding ke luar negeri yang hanya berujung pelesiran. Kini ditambah oleh “perayaan tunjangan” yang menegaskan betapa jauhnya jarak antara mereka dengan aspirasi masyarakat. Dalam perspektif komunikasi politik, simbol joget itu menjadi pesan nonverbal bahwa kepentingan pribadi lebih dominan daripada tanggung jawab kolektif.
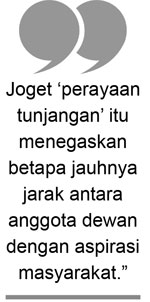 Di sinilah letak paradoksnya. Fungsi utama anggota dewan adalah memperjuangkan kepentingan rakyat, menyerap aspirasi, dan mengawasi pemerintah agar kebijakan prorakyat benar-benar berjalan. Namun, bagaimana mungkin mereka bisa dipercaya membela rakyat apabila saat rakyat melarat, mereka justru berjoget ria di atas panggung kemewahan?
Di sinilah letak paradoksnya. Fungsi utama anggota dewan adalah memperjuangkan kepentingan rakyat, menyerap aspirasi, dan mengawasi pemerintah agar kebijakan prorakyat benar-benar berjalan. Namun, bagaimana mungkin mereka bisa dipercaya membela rakyat apabila saat rakyat melarat, mereka justru berjoget ria di atas panggung kemewahan?
Kepercayaan publik terus tergerus dan apatisme politik meluas. Padahal, kepercayaan rakyat sangat penting di alam demokrasi. Jika rakyat kehilangan kepercayaan pada lembaga legislatif, legitimasi sistem politik ikut terkikis. Sudah sepantasnya rakyat menagih moralitas para wakilnya.
Jabatan publik adalah amanah, bukan fasilitas untuk bersenang-senang. Setiap rupiah tunjangan yang diterima anggota dewan sejatinya berasal dari keringat rakyat: para petani apel di Batu yang harus berhadapan dengan harga pupuk mahal, nelayan di pesisir Madura yang bergelut dengan cuaca buruk, buruh pabrik di Jawa Barat yang hidup dengan upah minimum, hingga pedagang kecil di pasar tradisional yang bertarung sengit dengan ritel modern.
Jika para anggota dewan bersorak bahagia atas kenaikan tunjangan tanpa peduli jeritan rakyat, mereka sejatinya sedang merayakan jarak yang makin lebar antara kemewahan elite dan keprihatinan hidup rakyat. Fakta itu sekaligus mengingatkan kita bahwa demokrasi bukan semata soal prosedur pemilu, melainkan juga soal moralitas dan rasa malu kaum pejabat. Demokrasi niscaya kehilangan maknanya apabila wakil rakyat hanya sibuk memikirkan kenyamanan pribadi.
Refleksi
Revolusi mental yang sering digaungkan semestinya tidak berhenti pada jargon politik, tetapi diwujudkan dalam perilaku nyata yang mencerminkan kesederhanaan, pengorbanan, serta keberpihakan kepada rakyat. Wakil rakyat kiranya berhenti mempertontonkan perilaku yang melukai nurani rakyat. Mereka perlu kembali meneguhkan jati diri sebagai pelayan publik, bukan penguasa anggaran.
Opini publik jelas menuntut perubahan. Momen kenaikan tunjangan seharusnya menjadi refleksi apakah kesejahteraan rakyat juga ikut meningkat atau justru hanya mempertebal kenyamanan kursi parlemen. Pertanyaan itulah yang wajib dijawab para anggota dewan. Bukan dengan joget, melainkan dengan kebijakan prorakyat.
Rakyat boleh jadi sudah terlalu sering tersakiti. Namun, setiap periode politik selalu menyisakan harapan baru, harapan agar dewan yang terhormat benar-benar menepati sumpahnya. Dengan begitu, wakil rakyat akan benar-benar layak disebut wakil, bukan pejoget di panggung politik.
Jika anggota dewan ingin memulihkan muruahnya, langkah awal yang harus diambil adalah mengubah perilaku simbolis yang tampak di depan publik. Mereka harus menunjukkan solidaritas dengan rakyat dalam kesederhanaan, kejujuran, dan komitmen. Kenaikan tunjangan hanya bisa diterima publik apabila diiringi peningkatan kinerja, transparansi, serta keberanian menolak segala bentuk korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Tanpa itu semua, joget anggota dewan hanya akan memperparah catatan hitam dalam sejarah parlemen Indonesia. (*)