Buka konten ini

Sastrawan Asal Lubuklinggau, Sumatra Selatan
Bagi saya, residensi menulis bukanlah istilah yang eksklusif untuk program-program resmi berselimut logo lembaga. Ia adalah laku, pilihan sadar untuk menepi dan memberi ruang bagi diri sendiri untuk bekerja dengan penuh perhatian. Ketika seseorang memutuskan menyingkir dari hiruk pikuk dan pindah ke lereng bukit di kampungnya demi bisa berkarya dengan lebih jernih, itu pun residensi. Tak perlu paspor, tak perlu undangan internasional. Yang dibutuhkan adalah kesediaan untuk diam, mengamati, dan menulis.
Itulah sebabnya, saya menjalani residensi—dalam pengertian ini—di banyak tempat dengan banyak alasan yang kadang bahkan tak ada hubungannya dengan “program” resmi. Saya pernah ke Turki dan Slovenia untuk urusan “ghost writing”. Karena waktunya cukup panjang, saya menjadikannya sekaligus sebagai periode residensi menulis.
Saya pernah menghabiskan waktu di Kepulauan Karimata. Awalnya untuk memenuhi undangan teman yang meminta saya mengajar anak-anak pulau menulis, Siapa sangka, pulau itu memberi saya bukan hanya murid, melainkan suasana hening dan udara asin yang membuat draf naskah saya selesai jauh lebih cepat dari yang saya bayangkan.
Kalau ditarik ke garis yang lebih panjang, pandemi 2020 hingga 2022 pun adalah residensi terpanjang saya. Bukan karena saya tinggal di luar negeri, melainkan karena saya—kita semua—dilempar ke tatanan dunia yang baru, asing, penuh kejutan, dan tak jarang menakutkan. Dalam keterbatasan gerak itu, saya justru belajar mengubah ruang menjadi laboratorium. Rumah menjadi studio. Jalan depan rumah menjadi galeri. Situasi itu, bagi saya, “lebih residensi” daripada residensi di negara mana pun, karena ia memaksa saya melihat ulang seluruh peta kreatif saya.
Mungkin itu sebabnya, saya percaya residensi bukan sekadar mencari “jalan lain menuju Roma”. Lebih dari itu, Anda bisa membangun “Roma” Anda sendiri—meskipun peta dan jalannya tak pernah disediakan untuk Anda. Saya mengucapkannya bukan dari teori, tetapi dari pengalaman yang agak getir: selama enam tahun berturut-turut (2016 s.d. 2021), saya tak pernah sekalipun lulus seleksi residensi menulis luar negeri yang ditaja sebuah komite bentukan pemerintah. Nama saya tak pernah muncul dalam daftar panjang itu—lebih dari enam puluh penulis Indonesia yang beruntung dibawa negara melanglang buana.
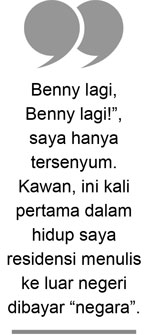 Awalnya, saya menganggapnya kebetulan, lalu menjadi tanda tanya. Lama-lama, saya belajar tertawa sendiri. Satire-nya begini: bahkan jika semua penulis di daftar itu digabung, tetap tak cukup untuk mengisi semua meja di warung kopi kampung saya—dan saya, yang duduk di pojok, tetap tak dipanggil.
Awalnya, saya menganggapnya kebetulan, lalu menjadi tanda tanya. Lama-lama, saya belajar tertawa sendiri. Satire-nya begini: bahkan jika semua penulis di daftar itu digabung, tetap tak cukup untuk mengisi semua meja di warung kopi kampung saya—dan saya, yang duduk di pojok, tetap tak dipanggil.
“Kegagalan” ini, yang mungkin bagi sebagian orang menjadi alasan untuk berhenti, justru membakar keinginan saya untuk mencoba jalur lain. Saya mendaftar ke banyak program kebudayaan, sastra, dan kesenian di luar Indonesia. Sebagian besar menolak. Yang tersisa membawa saya ke perjalanan yang tak pernah saya bayangkan: berproses kreatif di lebih dari dua puluh negara, dari kafe kecil di Ljubljana hingga ruang sunyi di Karimata, dari pasar buku di Istanbul hingga rumah panggung di pedalaman Sumatra.
Itu sebabnya, ketika pada 2025 saya diumumkan sebagai salah satu peserta Residensi Mancanegara yang ditaja Badan Bahasa—dibiayai APBN—dan komentar yang datang berbunyi: “Benny lagi, Benny lagi!”, saya hanya tersenyum. Kawan, ini kali pertama dalam hidup saya residensi menulis ke luar negeri dibayar “negara”. Selebihnya, Roma saya bangun sendiri, jalan saya aspal sendiri—dan mungkin itu sebabnya ia terasa begitu milik saya.
Pengalaman ini mengingatkan saya pada banyak kisah residensi “liar” yang lahir dari ketidakterdugaan. Ernest Hemingway menulis sebagian The Sun Also Rises di sebuah kafe di Pamplona, bukan karena ia mendapat undangan resmi, tapi karena ia sedang mengikuti festival adu banteng. Rabindranath Tagore melahirkan puisi-puisi terkenalnya saat berlayar di sungai Padma, jauh dari pusat-pusat kebudayaan. Di era modern, Haruki Murakami pernah bercerita bahwa beberapa novelnya selesai di rumah kayu kecil di pinggiran Tokyo—tanpa sponsor, tanpa seleksi, hanya karena ia ingin mengasingkan diri dari kesibukan kota.
Saya percaya, residensi yang baik lahir dari niat untuk memberi ruang pada diri sendiri, bukan dari stempel atau sertifikat. Program resmi tentu punya manfaat—jaringan, fasilitas, pengakuan,tetapi residensi yang tumbuh dari inisiatif pribadi sering kali lebih jujur: tidak dibatasi jadwal yang kaku, tidak diarahkan untuk memenuhi visi kurator, dan tidak dipaksa untuk menulis sesuatu yang “layak pamer”.
Jadi, ketika seseorang bertanya, “Di mana sebaiknya saya melakukan residensi?”, saya akan balik bertanya, “Di mana Anda ingin diam dan mendengarkan diri sendiri?” Itu bisa di loteng rumah nenek, di pojok perpustakaan kampus, di bangku panjang stasiun kecil, atau di kota asing yang Anda pilih tanpa alasan jelas.
Residensi, bagi saya, adalah urusan substansi, bukan validasi. Sebab Roma—atau apa pun nama yang Anda berikan—tak selalu berada di peta yang dibagikan orang lain. Kadang, ia menunggu di tempat yang hanya bisa ditemukan oleh kaki, mata, dan hati Anda sendiri. Ketika Anda menemukannya, Anda akan tahu: perjalanan itu milik Anda, sepenuhnya. (*)